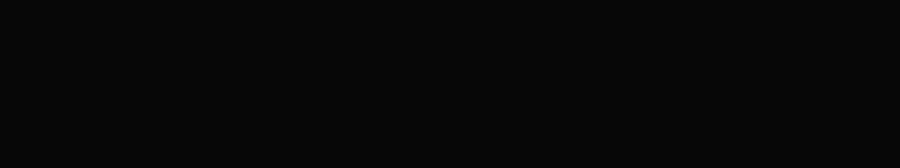JAKARTA, harianindonesia.id – Tahun ini, pengguna media sosial kita, terutama kalangan muda, kerap mengutip ungkapan Dilan kepada Milea. “Jangan rindu, Berat. Kamu nggak akan kuat, biar aku saja”. Ya, ungkapan itu ada di film Dilan 1990 yang tayang perdana Januari 2018.
Film yang diadaptasi dari dari novel berjudul sama karya Pidi Baiq tersebut bernuansa kisah cinta remaja SMA yang mendapatkan aprsiasiasi tinggi dari penonton.
Berdasarkan data Filmindonesia.or.id, Jumat 30 Maret, Dilan 1990 ditonton sekitar 6.314.986 orang. Selanjutnya Eiffel, I’m In Love dengan jumlah 1.008.392 penonton, Yowis Ben 928.640 penonton, Benyamin Biang Kerok dengan 740.196 penonton, dan Bayi Gaib: Bayi Tumbal dengan 617.045 penonton.
Bertepatan dengan Hari Film Nasional yang diperingati tiap tanggal 30 Maret, Abdullah Alawi dari NU Online berhasil mewawancarai sutradara film dokumenter Prison and Paradise Daniel Rudi Haryanto, pria kelahiran Semarang, 17 April 1978, lulusan Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta.
Prison and Paradise melanglang buana ke sejumlah festival bergengsi dunia seperti Yamagata International Documentary Film Festival pada tahun 2011, Cinema Digital CINDI International Film Festival 2011 (Korea Selatan), Montreal International Documentary Film Festival (RIDM) di Canada pada tahun 2011, Vibgyor Internastional Film Festival di Thrissur Kerala, India 2011, Tokyo Documentary Dream Show 2012, Asiatica Mediale di Roma Italia 2012, dan lain lain.
Kepada Rudi, NU Online bertanya seputar perkembangan kualitas dan kuantitas film Indonesia, serta strategi kebudayaannya. Berikut petikannya:
Bagaimana tema atau konten film Indonesia hari ini?
Saya melihat konten film Indonesia saat ini masih berkisar pada apa yang dulu pernah sukses, misalkan genre horor, komedi, dan epos kepahlawanan. Sama halnya dengan genre di masa lalu. Menariknya, soal soal teknis semakin membaik karena sebagian besar para pembuat film merupakan alumni sekolah film semacam Institut Kesenian Jakarta (IKJ).
Bisa dikatakan kualitas sama kuantitas lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya?
Kualitas teknis membaik dan kuantitas semakin banyak. Ini merupakan kabar baik bagi insan perfilman di Indonesia karena memunculkan harapan bagi masa depan pemasaran film karya orang Indonesia di Indonesia.
Faktor yang membuat perkembangan film Indonesia lebih membaik itu apa? Ada peran pemerintah di situ?
Faktor teknologi menjadi pendorong utama saya kira. Teknologi kamera digital telah melahirkan satu generasi awal yang menggunakan teknologi kamera video dan alat editing dan tata suara yang lebih praktis dan ringkas serta lebih murah untuk menghasilkan film.
Peranan pemerintah ada dan sudah baik dengan adanya Pusbang Film dan Bekraf. Tetapi dapat didorong lebih maksimal lagi. Seharusnya Pusbang Film menghasilkan bibir bibit filmmaker dalam konsep kebudayaan dan strategi kebudayaan. Sedangkan Bekraf memperkokoh dengan konsep industri yang terukur dan pencapaian yang terukur pula. Saat ini terasa sekali tumpang tindih keduanya.
Dari sisi regulasi, apa saat ini lebih mendorong atau malah memberatkan? Regulasi pemerintah yang mana yang dimaksud? Misalkan ada tidak UU perfilman yang dikeluhkan insan perfilman?
Biasanya masih seputar masalah sensor ya. Insan perfilman mengkritisinya dengan memberikan solusi klasifikasi. Menurut saya, klasifikasi adalah solusi yang tepat. Tentu ini perlu dibicarakan lebih lanjut antara organisasi perfilman, pemerintah dalam hal ini yang terkait dengan perfilman dan DPR. Sensor yang merupakan produk kebijakan di masa pemerintahan Orde Baru tidak berorientasi pada pembangunan industri dan strategi kebudayaan akan tetapi mengacu pada pelanggengan kekuasaan.
Bisa diceritakan yang dimaksud klasifikasi sebagai solusi sensor itu seperti apa?
Klasifikasi dapat berupa klasifikasi umur, misalkan film-film yang terkait dengan konten dewasa layak ditonton untuk 17 tahun ke atas. Tetapi soal klasifikasi ini saya berpendapat, itu jika sistem industri sudah terjadi sehingga distribusi film dapat terkontrol. Kita belum ada industri sehingga saya kira soal soal klasifikasi ini perlu dibahas lebih lanjut oleh para pelaku industri film Indonesia dan pelaku film sebagai strategi kebudayaan.
Soal tematik juga bagian dari klasifikasi. Soal tematik terkait dengan umur penonton. Tema-tema yang mengandung konten seks misalkan, diklasifikasikan untuk yang sudah layak umurnya dewasa. Tema politik misalkan atau kekerasan juga harus dapat diklasifikasikan untuk mereka yang sudah mampu mengenyam tontonan semacam itu. Tema yang umum dapat dikonsumsi oleh semua umur juga perlu ditentukan.
Strategi kebudayaan film kita. Lembaga Sensor Film yang sampai hari ini masih menjadi bagian dari status quo, semestinya dapat direformasi menjadi badan atau lembaga yang menentukan klasifikasi. Soal-soal tema yang dianggap sensitif misalkan seharusnya dapat dirembuk bersama stakeholder perfilman, bukan atas dasar sepihak dari lembaga sensor film yang mana dalam praktiknya belum tentu penyensor memiliki pemahaman terhadap estetika dan teknis film.
Tadi menyebut strategi kebudayaan. Bisa dijelaskan?
Strategi kebudayaan yang saya maksud adalah jika anda menemukan anak pesantren tergila gila sama lagu, tarian, fashion Kpop (Korean pop) itu bukan suatu kebetulan. Itu merupakan hasil dari ekspansi budaya Korea yang dirumuskan dan didesain oleh para pemangku kebudayaan Korea untuk memperkuat politik kebudayaan mereka. Kalau Anda melihat Superman dan superhero sekarang cawetnya di dalam itu bukan kebetulan belaka. Itu strategi Hollywood untuk ekspansi pada market Asia dan Timur Tengah yang berkembang sebagai masyarakat dengan ekonomi yang dapat membelanjakan menonton film dan hiburan berikut membeli segala mercendise yang mereka produksi.
Saya punya cita cita, Indonesia mampu merumuskan strategi kebudayaan dalam memperkokoh politik kebudayaan kita sehingga anak anak Korea, Jepang, Eropa tergila-gila sama batik, gamelan, sape gitar dayak, tari pendet, tari sedati, tarian burung dayak atau syari syair kearifan lokal Nusantara.
Lalu strategi kebudayaan film kita bagaimana untuk berbuat yang sama seperti mereka?
Kita harus mampu merumuskan itu seperti halnya Usmar Ismail berjuang merumuskan Sinema Indonesia pasca revolusi 1945 dengan gerbong Lesbumi tetapi menginspirasi semua pihak. Dan itu hari ini belum berlanjut.
Kita dapat berangkat dari memeriksa ulang pemikiran pemikiran Bung Usmar Ismail, Bung Djamaluddin Malik, Bung Bachtiar Siagian untuk melanjutkan rumusan strategi kebudayaan nasional Indonesia dan politik kebudayaan kita di bidang film.
Kenapa itu tidak atau belum berlanjut?
Saya tidak tahu kenapa. Kita perlu kaji lagi.
Di seni rupa, konon, kita masih berkiblat ke Barat karena pelaku dan pengamat didikan sekolah dengan kurikulum Barat. Apa di film berlaku hal sama?
Agak sulit menyampaikannya. Film produk Barat itu betul. Saya kira yang perlu dibahas bukan soal Barat atau Indonesia. Itu paradigma yang enggak akan selesai. Yang penting dibahas sekarang adalah bagaimana kita mampu melahirkan industri film yang berkeadilan. Hulu hilir. Dari mulai sekolah film, perusahaan filmnya, asosiasi profesi film, komunitas, lembaga keuangan untuk modal produksi, distribusi, promosi film, media massa pemberitaan film, storasi dan literasi film dan lain lain. Pendidikan bisa dari mana saja tetapi kesadaran terhadap hasil pendidikan itu mau ke mana? Itu yang lebih penting. Seperti halnya di seni rupa. Tiap tahun sarjana seni rupa lulus, apakah semua karya mereka dibeli galeri? Tidak juga. Lantas siapa yang harus memikirkan si terdidik untuk dapat menjalani masa depan dengan keahlian atau skillnya? Siapakah yang dapat membuat sistem dari mulai pasar seni, ruang eksibisi, hingga marketnya?
Itu yang saya kira lebih penting daripada membicarakan soal dominasi Barat atau Indonesia karena persoalan Barat atau Indonesia itu malah sebenarnya jadi jebakan batman buat kita sendiri yang tidak sadar bahwa kita tak pernah lepas dari monopoli distribusi film asing di Indonesia yang masih dikuasai oleh sindikat tertentu
Oh ya, tiap tanggal 30 Maret diperingati sebagai Hari Film Nasional, ditetapkan berdasarkan hari pertama pengambilan gambar film Darah dan Doa. Bagaimana pandangan Anda tentang film karya Usmar Ismail itu? Apa istimewanya?
Sama istimewanya dengan film Bycicle Thief yang melahirkan mazhab neorealisme Italia. Darah dan Doa menjadi semangat pergumulan estetika dan revolusi bagi Usmar Ismail dan kawan kawan seperjuangan. Lebih istimewanya, film ini menyatakan realitas perjuangan bukan glorifikasi revolusi. Usmar dan kawan kawan mengerjakan film itu dengan gerilya sinema, menggunakan alat yang ada di masa krisis perang, sebuah film yang penting dalam sejarah sinema Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan 1945.