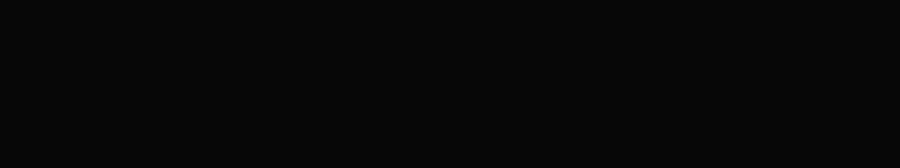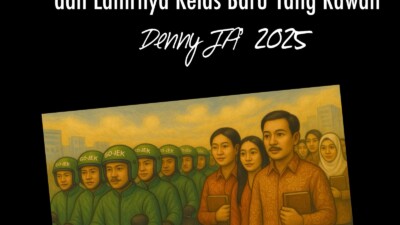– Artis Hollywood, Kampus Terkemuka, Aksi Massa dan Pemerintahan Resmi
Oleh Denny JA
Suatu sore di Ramallah, di Tepi Barat (West Bank), seorang anak perempuan Palestina bernama Rania berlari di jalanan sempit yang masih menyisakan bau mesiu.
Tangannya menggenggam buku catatan lusuh yang di sampulnya tertulis “free”. Ia menulis di sana cita-citanya: ingin suatu hari belajar di universitas besar dunia tanpa harus menunjukkan paspor sementara yang tak pernah diakui.
Sebagai warga Palestina, ia dianggap tak punya negara. Saat itu dunia barat menutup mata dengan isu Palestina merdeka.
Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya, di depan gerbang Columbia University di New York, ratusan mahasiswa mendirikan tenda solidaritas.
Mereka berteriak serempak, “Free Palestine!” Di London, ribuan orang memadati Trafalgar Square, melambaikan bendera hijau-putih-hitam dengan mata berkaca-kaca.
Dan di Los Angeles, artis Hollywood terkenal Emma Stone dan Mark Ruffalo berdiri di panggung Emmy Awards, mengenakan pin keffiyeh, berkata: “Kebebasan Palestina adalah kebebasan kita semua.”
Dunia Rania yang terkurung tembok itu kini menggema hingga jantung dunia Barat.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, narasi Palestina tidak lagi berbisik di pinggiran, tetapi menggema lantang di pusat peradaban global.
-000-
Ini Fenomena yang Belum Pernah Terjadi dalam sejarah.
Dukungan Barat pada Palestina merdeka kini bukan lagi wacana pinggiran.
Inggris, Kanada, dan Australia secara resmi mengakui negara Palestina, disusul Portugal, dan Prancis yang bersiap menyatakan hal serupa di Sidang PBB.
Dari pusat budaya pop, Hollywood, deretan bintang dunia—dari Billie Eilish hingga Pedro Pascal, dari Olivia Colman hingga Riz Ahmed—secara terbuka menyatakan dukungan.
Mereka menandatangani petisi, memboikot film produksi Israel, hingga mengangkat tema Gaza di ajang penghargaan bergengsi.
Di kampus-kampus elite, mahasiswa mendirikan tenda solidaritas: Harvard, MIT, UC Berkeley, Yale, Oxford, Cambridge. Mereka menuntut universitas melakukan divestasi dari perusahaan yang terlibat dalam pendudukan.
Fenomena ini adalah titik balik peradaban: solidaritas pada Palestina kini menjadi arus utama di jantung dunia Barat.
-000-
Tiga Penyebab Titik Balik
1. Ledakan Informasi Visual
Sejak 7 Oktober 2023, dunia menyaksikan tragedi Gaza bukan lagi lewat laporan diplomatik dingin atau editorial media yang terfilter.
Mereka melihat derita itu langsung melainkan melalui tayangan langsung di ponsel banyak orang.
Seorang ayah Palestina yang menggali anaknya dari reruntuhan. Seorang ibu yang menangis di lorong rumah sakit yang gelap. Anak- anak yang belajar menulis di tenda pengungsian. Semua itu menyebar viral.
Teknologi smartphone dan platform sosial media seperti TikTok, Instagram, dan X telah menciptakan demokratisasi informasi.
Narasi resmi yang selama puluhan tahun didominasi pro-Israel tak lagi mampu membendung derasnya arus visual. Fakta di lapangan menjadi “kesaksian global”, melintasi sensor media dan propaganda.
Inilah revolusi empati digital. Gambar menjadi argumen, air mata menjadi data, dan jeritan menjadi narasi tandingan.
Generasi muda Barat—yang hidup dengan budaya scrolling cepat—tak bisa berpaling. Mereka digiring dari ruang privat layar ke ruang publik demonstrasi.
Maka, runtuhlah monopoli lama. Jika dahulu opini publik bisa dibentuk lewat satu arah media, kini realitas di Gaza sendiri yang berbicara langsung kepada dunia.
Itulah yang membuat solidaritas meledak: ketika penderitaan tidak lagi jauh dan asing, melainkan hadir di genggaman setiap tangan.
-000-
2. Generasi Baru dan Politik Moral
Generasi Z dan milenial Barat tumbuh dalam lanskap etika global yang berbeda.
Mereka adalah generasi yang sadar iklim, menolak rasisme, mendukung kesetaraan gender, dan menuntut institusi publik hidup sesuai standar moral.
Bagi mereka, diam atas Palestina berarti menjadi kolaborator ketidakadilan.
Di universitas elite, mahasiswa tak hanya protes, mereka membangun narasi dekolonial: Palestina adalah wajah terakhir kolonialisme abad 21.
Solidaritas pun melebur dengan identitas politik: mendukung Palestina sama artinya mendukung keadilan global.
Itu sama seperti melawan apartheid, dan berdiri di sisi sejarah yang benar.
Lebih jauh, generasi baru ini memiliki toolkit politik berbeda: mereka membentuk jaringan lintas negara lewat media sosial, mengorganisir donasi digital, hingga menekan universitas melakukan divestasi.
Dalam kultur Barat, kampus adalah “jiwa bangsa.” Ketika mahasiswa mengguncang kampus, maka jantung moral peradaban ikut bergetar.
Fenomena ini menandai pergeseran otoritas: bukan lagi elit politik yang menentukan arah opini publik, melainkan suara kolektif generasi muda yang membawa beban etis dunia.
Mereka menolak warisan politik lama yang bias, dan berani membentuk norma baru. Palestina merdeka bukan sekadar isu luar negeri, melainkan cermin kemanusiaan mereka sendiri.
-000-
3. Multipolarisme Dunia
Hegemoni tunggal Amerika Serikat retak. Bangkitnya Tiongkok, India, Rusia, dan aliansi BRICS menghadirkan tatanan multipolar.
Negara-negara Barat yang dulu selalu “mengikuti Washington” kini punya ruang manuver.
Dulu, mendukung Palestina dianggap “bunuh diri politik.” Kini, ada kalkulasi baru: keuntungan geopolitik bisa diperoleh tanpa lagi harus selalu menyesuaikan diri dengan garis keras Israel-AS.
Inggris—negara yang sejak Deklarasi Balfour 1917 justru menjadi sponsor berdirinya Israel—kini berani berbalik. Itu tanda bahwa dinamika kekuasaan global benar-benar bergeser.
Multipolarisme membuka ruang bagi keberanian moral. Uni Eropa, yang dulu takut perpecahan internal, kini melihat peluang untuk tampil sebagai penyeimbang moral global.
Negara-negara seperti Portugal dan Belgia merasa lebih aman secara diplomatik untuk berdiri di sisi Palestina.
Di dunia multipolar, legitimasi moral kembali menjadi “mata uang politik.” Palestina merdeka bukan hanya isu keadilan, melainkan juga strategi membangun citra baru Barat di hadapan dunia Global South.
-000-
Sampai Kapan Israel dan Amerika Menolak?
Namun, di tengah gelombang dukungan itu, Israel tetap bertahan pada narasi keamanan. Dan AS masih menahan veto di PBB.
Sejarah menunjukkan, imperium yang menolak perubahan bisa bertahan lama, tetapi akhirnya selalu runtuh di hadapan arus moral zaman.
Israel dan Amerika bisa menunda, tapi tidak bisa membungkam. Jika Inggris saja—yang sejak Deklarasi Balfour 1917 menjadi fondasi berdirinya Israel—kini berbalik mendukung Palestina, maka waktu bukan lagi berpihak pada status quo.
Apakah ini berarti two-state solution akan berhasil?
Dunia kini lebih dekat dari sebelumnya. Dukungan formal negara Barat menciptakan tekanan diplomatik riil.
Untuk pertama kalinya, Palestina memiliki basis legitimasi di pusat kekuatan global, bukan hanya di dunia Arab atau Global South.
Meski gelombang dukungan global menguat, realitas di lapangan tetap kompleks. Fragmentasi kepemimpinan Palestina (rivalitas Hamas–Fatah) dan ekspansi permukiman Israel yang masif di Tepi Barat.
Diperkirakan lebih dari 500.000 pemukim Israel di area Tepi Barat (eksklusif Yerusalem Timur) dan tambahan sekitar 233.600 pemukim di Yerusalem Timur pada akhir 2024. Ini masih menjadi tantangan struktural.
Di sisi lain, BRICS dan ASEAN secara konsisten menyuarakan dukungan pada solusi dua negara berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB.
Namun dukungan BRICS dan ASEAN sejauh ini lebih bersifat politik-diplomatik, walau menegaskan hak rakyat Palestina atas penentuan nasib sendiri, mendesak penghentian kekerasan, dan menyerukan dimulainya kembali negosiasi damai.
Prediksi saya: two-state solution tidak akan lahir instan. Ia ibarat benih yang baru ditanam—membutuhkan waktu, tekanan internasional, dan keberanian civil society Israel-Palestina untuk menembus lingkaran setan kekerasan.
Tapi, gelombang dukungan ini adalah tiket sejarah. Jika arus moral Barat terus menguat, Israel akan dipaksa memilih: hidup damai berdampingan atau kian terisolasi seperti apartheid Afrika Selatan di masa lalu.
Dunia multipolar, generasi baru, dan revolusi informasi visual menciptakan ekosistem baru: dua negara bukan lagi ilusi, tetapi cita-cita yang makin dekat.
-000-
Apa yang bisa kita renungkan? Bahwa kebenaran sejarah selalu mencari jalannya sendiri. Tembok bisa didirikan, veto bisa dipakai, media bisa dibungkam.
Namun, ketika hati nurani miliaran manusia bergerak, ia menjelma arus besar yang tak bisa dihentikan.
Rania di Ramallah mungkin masih menulis di buku catatannya, di bawah lampu redup yang sering padam.
Tapi kini, untuk pertama kalinya, dunia Barat mendengar suaranya. Dari New York hingga Paris, dari Los Angeles hingga Oxford, suara itu bergema:
“Palestina merdeka adalah takdir moral zaman kita.”***
Jakarta, 22 September 2025
REFERENSI
1. Rashid Khalidi. The Hundred Years’ War on Palestine: A History of Settler Colonialism and Resistance, 1917–2017. (Metropolitan Books, 2020).
2. Edward Said. The Question of Palestine. (Vintage Books, 1992).
-000-
Ratusan esai Denny JA soal filsafat hidup, political economy, sastra, agama dan spiritualitas, politik demokrasi, sejarah, positive psychology, catatan perjalanan, review buku, film dan lagu, bisa dilihat di FaceBook Denny JA’s World
https://www.facebook.com/share/p/1AkKkEWVhi/?mibextid=wwXIfr