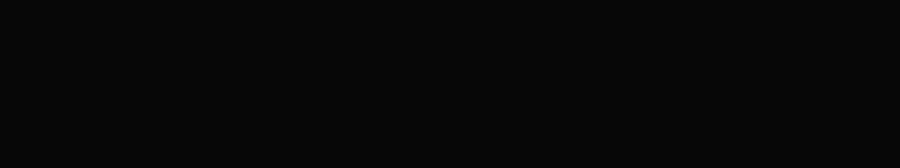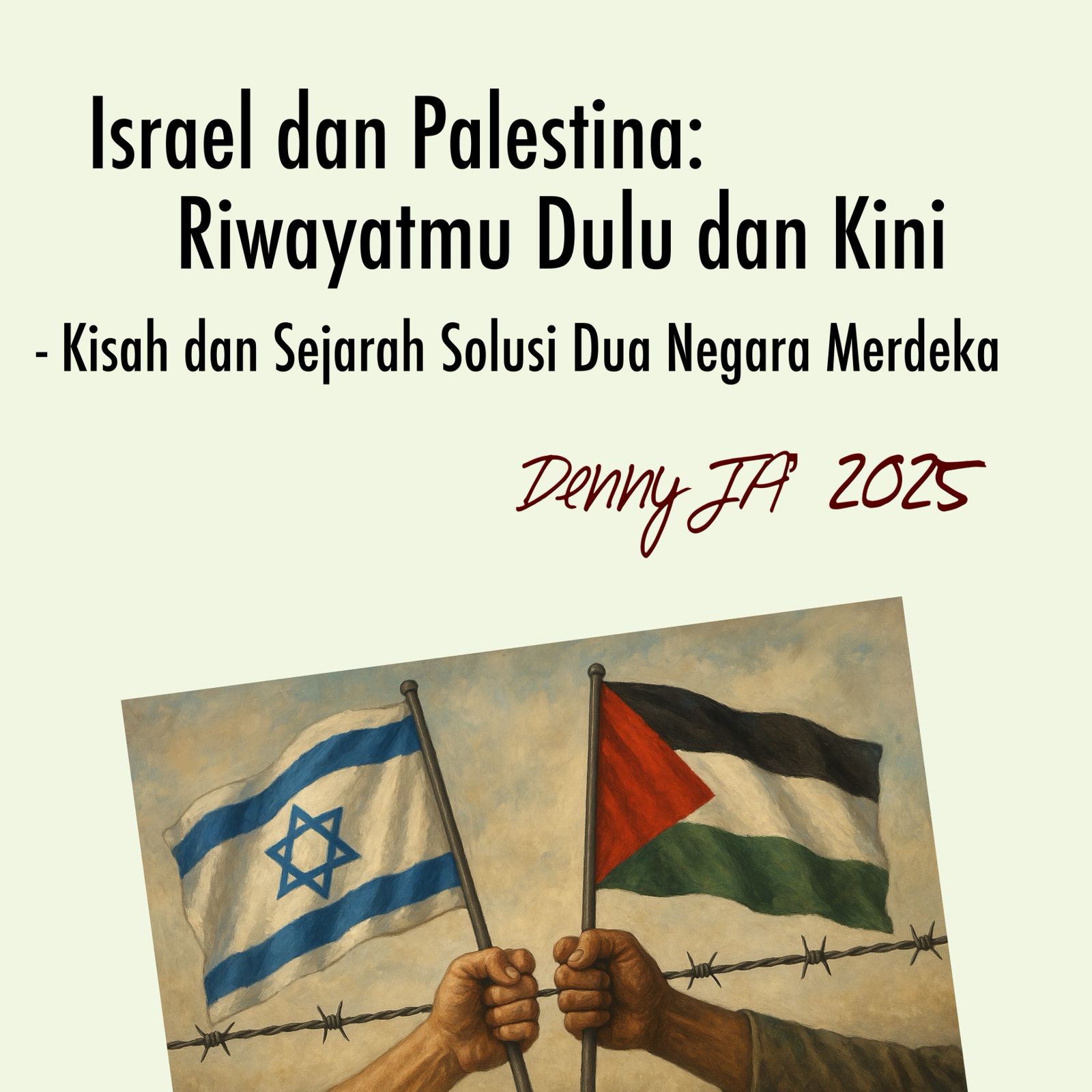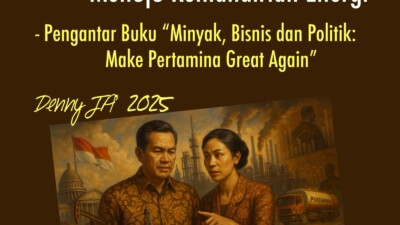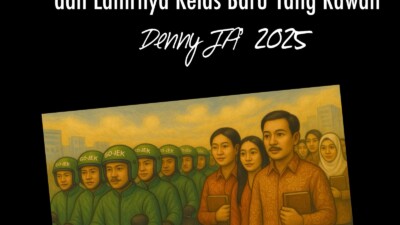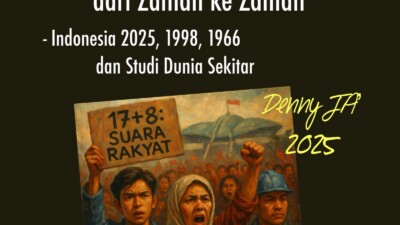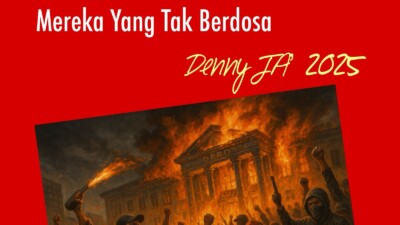– Kisah dan Sejarah Solusi Dua Negara Merdeka
Oleh Denny JA
Pada malam yang hening di Gaza City. Seorang anak lelaki bernama Yusuf berlari ke bawah tanah bersama keluarganya. Ledakan menggetarkan rumah-rumah, kaca pecah, dan langit dipenuhi cahaya merah.
Yusuf menggenggam erat tangan adiknya yang masih balita. “Apakah kita akan punya rumah lagi?” tanya adiknya polos. Yusuf tak bisa menjawab.
Ribuan kilometer jauhnya, di Ramallah, seorang ibu bernama Mariam duduk di beranda. Ia membuka radio kecilnya.
Suara penyiar internasional terdengar: “Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal kini mengakui Palestina merdeka. Prancis akan segera membuka kedutaan di Ramallah sebagai simbol dukungan.”
Mariam meneteskan air mata. Setelah puluhan tahun hidup dalam status “bangsa tanpa negara,” kabar itu baginya adalah cahaya baru di ujung lorong panjang penderitaan.
Dan di Paris, di sebuah ruangan megah di Quai d’Orsay, para diplomat Prancis merancang peta jalan pembukaan kedutaan resmi mereka di Palestina.
Di balik kaca jendela, menara Eiffel berdiri anggun. Kota cahaya itu seakan ikut bersinar untuk sebuah bangsa yang lama hidup dalam kegelapan.
Kisah Yusuf, Mariam, dan Paris hanyalah sekelumit mosaik dari sejarah panjang. Palestina bukan hanya tragedi lokal, melainkan cermin moral dunia.
-000-
Awal Mula Two-State Solution
Gagasan solusi dua negara — Israel dan Palestina hidup berdampingan sebagai dua negara merdeka — bukanlah ide baru.
Akar historisnya muncul dari tahun 1947. Itu ketika Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi 181.
Resolusi ini mengusulkan pembagian tanah Mandat Palestina menjadi dua negara. Satu untuk Yahudi, satu untuk Arab Palestina, dengan Yerusalem sebagai wilayah internasional.
Namun sejarah menempuh jalannya yang berdarah. Pada 1948, Israel mendeklarasikan kemerdekaan. Lalu disusul perang yang menyebabkan Nakba: 750.000 orang Palestina terusir dari rumah mereka.
Solusi dua negara terkubur oleh kekerasan, perang 1967. Proyek kolonial permukiman yang terus meluas.
Di dekade 1990-an, solusi dua negara kembali mengemuka melalui Perjanjian Oslo (1993). Dunia menaruh harapan. Tangan Yasser Arafat dan Yitzhak Rabin berjabatan di halaman Gedung Putih, disaksikan Bill Clinton.
Namun harapan itu runtuh karena perluasan permukiman, kegagalan implementasi, dan lingkaran kekerasan yang berulang.
Solusi dua negara adalah janji yang selalu hadir di meja diplomasi. Tetapi ia selalu tertunda di medan realitas.
-000-
Perkembangan Kini: Arus Balik Dunia
Hari ini, kita menyaksikan perubahan besar. Gelombang dukungan untuk Palestina semakin deras datang dari Barat. Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal telah mengakui Palestina.
Prancis, simbol budaya dan diplomasi Eropa, berencana membuka kedutaan di Palestina. Ini langkah bersejarah yang memperkuat legitimasi internasional.
Puncaknya, pada 21 September 2025. Prancis dan Arab Saudi memimpin pertemuan di markas besar PBB, New York.
Puluhan pemimpin dunia hadir, termasuk Presiden RI, Prabowo Subianto. Pertemuan itu menegaskan kembali dukungan untuk solusi dua negara.
Namun Israel menyebutnya “sirkus,” dan Amerika Serikat memperingatkan akan ada konsekuensi bagi negara yang “menentang Israel.”
Di balik retorika diplomasi, di lapangan perang terus berkecamuk. Israel menggempur Gaza City, menambah daftar panjang korban sipil.
Tetapi justru dari penderitaan itulah lahir solidaritas baru. Untuk pertama kalinya, pusat-pusat kekuatan global di Eropa Barat menyuarakan dukungan terbuka, bukan lagi basa-basi diplomasi.
-000-
Tiga Penyebab Inggris dan Prancis Kini Mendukung Palestina
1. Beban Sejarah dan Penebusan Moral
Inggris adalah tanah lahirnya Deklarasi Balfour 1917. Ini sebuah dokumen singkat yang menjanjikan tanah Palestina kepada Zionis sambil mengabaikan mayoritas penduduk Arab.
Dokumen itu menyalakan api yang terus membakar hingga kini. Generasi baru pemimpin Inggris tak bisa lagi menutup mata pada tanggung jawab sejarah.
Mengakui Palestina hari ini adalah bentuk penebusan moral atas luka yang lahir lebih dari seabad lalu.
Prancis pun punya jejak kolonial di Timur Tengah dan Afrika Utara. Dari Aljazair hingga Tunisia, kolonialisme meninggalkan trauma yang masih hidup di tubuh diaspora Arab di Prancis.
Dengan mengakui Palestina, Prancis mengirim pesan: “Kami belajar dari sejarah, dan kami tidak lagi berpihak pada kolonialisme modern.”
-000-
2. Tekanan Politik Domestik dan Demografi Baru
Di Inggris, komunitas Muslim sudah mencapai hampir 7% populasi. Di Prancis, lebih dari lima juta penduduk adalah keturunan Arab–Maghreb.
Generasi muda diaspora ini kini menjadi bagian penting dari politik domestik: anggota parlemen, intelektual, aktivis, hingga selebritas.
Mereka tidak lagi sekadar minoritas yang diam. Saat Gaza dibombardir, ribuan orang turun ke jalan di London dan Paris. Suara massa ini tidak bisa diabaikan.
Para pemimpin politik membaca gelombang moral sekaligus elektoral: mengakui Palestina adalah juga cara merangkul rakyatnya sendiri.
-000-
3. Strategi Geopolitik: Reposisi Barat di Dunia Multipolar
Eropa menyadari dirinya lama terjebak dalam bayang-bayang Washington. Namun multipolarisme dunia membuka ruang manuver.
Dengan mengakui Palestina, Inggris dan Prancis ingin menunjukkan kedaulatan diplomatik: bahwa mereka bisa mengambil keputusan moral meski berseberangan dengan Amerika Serikat dan Israel.
Prancis, dengan tradisi gaullisme yang menekankan kemandirian politik luar negeri, memanfaatkan momen ini untuk memperkuat citra sebagai penyeimbang global.
Inggris, yang baru keluar dari Uni Eropa, ingin membuktikan masih memiliki bobot moral di panggung dunia.
Dukungan terhadap Palestina adalah kartu geopolitik. Ini melawan dominasi, sekaligus membangun kredibilitas di hadapan Dunia Selatan.
-000-
Dari perspektif sejarah, Palestina adalah bangsa yang sudah seabad menunggu. Dari perspektif budaya, Palestina adalah simbol ketabahan dan kegigihan.
Dari perspektif filsafat, Palestina adalah pertanyaan moral: apakah dunia benar-benar peduli pada keadilan universal, ataukah hanya tunduk pada logika kekuasaan?
Solusi dua negara mungkin belum tuntas hari ini. Israel dan Amerika Serikat masih menolak keras. Tetapi sejarah menunjukkan: tembok bisa bertahan puluhan tahun, namun runtuh juga pada akhirnya.
Apartheid di Afrika Selatan pernah tampak abadi, hingga tumbang di hadapan arus moral global.
Di tengah kompleksitas ini, solusi dua negara membutuhkan keberanian visioner. Yaitu
pengakuan Israel atas hak Palestina untuk eksis sebagai bangsa berdaulat. Sebaliknya, Palestina mengakui trauma historis Yahudi.
Peran mediator netral
(misalnya ASEAN atau Afrika Selatan) bisa memutus siklus ketidakpercayaan.
Sementara investasi global dalam rekonstruksi Gaza dan pendidikan perdamaian menjadi katalisator rekonsiliasi.
Palestina adalah luka dunia, tapi juga kompas moralnya. Jika bangsa itu suatu hari merdeka, maka dunia telah menyembuhkan sebagian dari luka peradabannya sendiri.
Seperti Yusuf di Gaza yang berlari bersama adiknya, dan Mariam di Ramallah yang meneteskan air mata mendengar kabar pengakuan baru, kita belajar satu hal: bahwa kebenaran sejarah selalu mencari jalannya.
Dan ketika kebenaran itu tiba, suara dunia akan bergema dalam satu kalimat sederhana:
“Dua bangsa, dua negara, hidup merdeka berdampingan.”***
Jakarta, 23 September 2025
Referensi
1. Edward Said, The Question of Palestine. Vintage Books, 1992.
2. Rashid Khalidi, The Hundred Years’ War on Palestine: A History of Settler Colonialism and Resistance, 1917–2017. Metropolitan Books, 2020.
-000-
Ratusan esai Denny JA soal filsafat hidup, political economy, sastra, agama dan spiritualitas, politik demokrasi, sejarah, positive psychology, catatan perjalanan, review buku, film dan lagu, bisa dilihat di FaceBook Denny JA’s World
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0LhY5bqdsKoSWC4XFHF1PMBLnWwpCwFsJvLgFKhQNP2ApdNwCLo5tN9pchSfnFs4gl&id=100044483107470&mibextid=wwXIfr