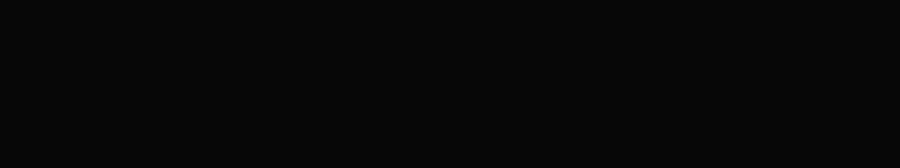JAKARTA, harianindonesia.id – HARI Pers Nasional (HPN), yang tak semua insan pers Indonesia sepakat Keputusan Presiden RI No. 5/1985 tentang HPN tiap 9 Februari, jelas janganlah sekadar seremoni prosesi berganti provinsi tiap tahunnya.
Ada sejumlah posisi paradoks tajam kekinian di antara berbagai progresivitasnya, sehingga beragam kontras menyembul–terutama dalam era tsunami informasi sekarang– adalah bahan retropeksi untuk bahan solusi bersama.
Pertama, wajah sebagian besar media massa hari ini kian memperlihatkan watak dan preferensi karakternya yang partisan.
Tak sekadar partisan, beberapa sudah “terjerumus” dalam pola cinta berlebih dan benci akut (hater and lover) yang kian menyeruak pasca-Pemilu Presiden 2014.
Sekalipun sudah ditulis sejak lama, tepatnya tahun 1984, profesor jurnalistik di Indiana University, Amerika Serikat, J Herbet Altschull, kiranya masih tetap memiliki pemikiran relevan terkait media massa dan jurnalisme Indonesia kontemporer.
Dalam Agent of Power, Herbet menulis premis pada tahun itu, nyaris 35 tahun silam, bahwa konten media sebenarnya selalu memperlihatkan kepentingan pemilik modalnya (the content of the media always reflect the interest of those who finance them).
Kalakian, hari ini ketika peradaban masyarakat harusnya kian berderap maju, pemikiran tersebut bukan sekedar relevan –terutama jika kita melihat praktik penyiaran televisi free to air yang dimiliki pengusaha dan politisi sejak Pilpres 2014.
Bangsa Indonesia umumnya dan masyarakat Jawa Barat khususnya malah menjadi korban konten partisan yang menyokong haluan politik sang empunya. Sekaligus masyarakat pun dijauhkan dari hak ideal memperoleh informasi produk jurnalistik yang baik dan benar.
Kita kemudian jadi kangen, rindu teramat betapa tajamnya jurnalistik free to air television dalam menyuarakan aspirasi rakyat.
Ini bukan angan-angan karena mengacu literatur, seperti “Media dan Kekuasaan” (Ishadi SK: 2014), motor utama penumbang Orde Baru salah satunya adalah siaran televisi gratisan tersebut.
Faktanya, masyarakat Indonesia berkat diseminasi informasi tadi malah terperangkap terpaan pesan komunikasi massa nuansa hater and lover, yang selain terus memecah-belah, juga sulit memberikan ruang bersama sebagai sebuah layanan utama media massa.
Kedua, tren global, regional, dan kini masif terjadi ke Indonesia atas peralihan membaca media massa konvensional, sungguh tak serta-merta meningkatkan sirkulasi ekonomi pada media baru berbasis digital (new media).
Saat, misalnya, oplah dan tiras media cetak terus menukik, para praktisi media tak pernah surut harap karena di saat bersamaan, terjadi perpindahan habitual pembaca dari koran/tabloid/majalah ke kanal digital.
Jadilah, berbondong-bondonglah media massa melahirkan platform digitalnya guna mengakomodasi perubahan perilaku tersebut.
Tentu, semuanya pede, dengan sendirinya akan terjadi perpindahan bisnis media itu sendiri. Kenyataannya? Tidak!
Ambil contoh di Jawa Barat, sebab ini provinsi terbesar di Indonesia dengan 47 juta penduduk.
Pada tahun lalu, total tiras seluruh koran diasumikan sekitar 500.000 sampai 600.000 koran per hari. Jika diasumsikan satu koran dibaca tiga orang, maka oplahnya 1,5 juta orang.
Jumlah penduduk Jawa Barat sendiri akhir tahun 2017 mencapai 47 juta, dengan usia produktif sekitar 65 persen di antaranya (30 juta)
Dengan demikian, penetrasi keterbacaan adalah masing-masing mencapai 3,191 persen dari total penduduk serta 5 persen dari usia produktif.
Angka sebesar ini berbanding lurus pertumbuhan pengguna internet di Jabar kisaran 15 persen dari total pengguna internet Indonesia tahun lalu kisaran 120 juta atau 18 juta orang. Jadi, estimasi angka pembaca new media 12 kali lipat dari total pembaca koran!
Banyak survei menyebutkan bahwa motivasi mencari informasi adalah motif kedua mengakses internet setelah akses media sosial. Artinya, ada potensi pasar bagi media dan para pemasang iklan di sini.
Akan tetapi, fakta di lapangan, iklan dan berbagai material bisnis reguler tidak serta-merta pindah semuanya ke laman berita dari media cetak yang bahkan sudah berusia puluhan tahun lamanya di Tatar Sunda.
Penulis kerap menerima keluhan dari para praktisi media massa, sekalipun pembaca menurun, pengiklan masih tetap memilih bentuk konvensional. Anomali ini membuat investasi di kanal digital yang dikeluarkan tak cepat berbuah manis.
Data secara nasional setali tiga uang. Nielsen Advertising Information Services menunjukkan, total belanja iklan 2016 sebesar Rp 134,8 triliun atau tumbuh 14 persen dari tahun sebelumnya.
Ini meneruskan tren kenaikan dari tahun 2012 Rp 84,3 triliun, 2013 (Rp 101,9 triliun), 2014 (Rp 110 triliun), dan 2015 (Rp 118 triliun).
Sekalipun demikian, alokasi belanja masih ke media konvensional, yakni didominasi 77 persen televisi, koran 22 persen, dan majalah 1 persen. Sisanya, yakni hanya 2 persen, diperebutkan oleh radio dan termasuk media massa daring.
Anomalitas makin terasa karena Nielsen menyebutkan, jika pada 2012 ada 102 koran yang diteliti, maka tahun 2016 hanya 98 koran.
Demikian pula majalah, berkurang dari 162 menjadi 120, sehingga logikanya seharusnya ada peralihan belanja iklan dari media cetak ke media daring tersebut.
Faktanya, sekali lagi, pengelola media daring (sekalipun derivatif media cetak besar) masih gigit jari karena belum menemukan model bisnis ideal. Situasi ini diperumit para pengambil keputusan pada perusahaan pemasang iklan.
Dengan mayoritas termasuk golongan digital immigrant alias belum punya wawasan dan kepercayaan diri tinggi terhadap media baru, mereka tetap memilih berbelanja iklan di media tradisional sekalipun terjadi perubahan signifikan perilaku pembaca.
Hal ini menjadi paradoksial kedua karena di banyak negara maju, peralihan bisnis ke new media tersebut nyata terjadi bahkan signifikan.
The Nieman Jurnalism Lab, Amerika Serikat (2017) menuliskan, ketika iklan versi cetak The New York Times turun 11 persen menjadi 77 juta dollar AS per Januari-Juni 2017, maka pada waktu bersamaan, tumbuh iklan versi daring 23 persen menjadi 55 juta dollar AS.
Koran terbesar di Swedia, AftonBladet, pada tahun 2016 mencatat pendapatan iklan terbesar dari versi digital.
Ini berkat kesuksesan perolehan pembaca laman daring mereka via gawai sebanyak 2,5 juta orang sementara pembaca koran mereka 600.000 dari oplah 150.000 koran.
Kelompok media ternama Jerman, Die Welt, meraih laba 2016 sebesar 595 juta euro dengan 67 persen kontribusi berasal dari lini daring mereka.
Mengapa berbeda tajam di Indonesia? Hal ini perlu penjelasan terpisah dan tersendiri, namun singkatnya karena budaya membeli konten daring digital nyaris tiada di Indonesia tercinta ini.
Ketiga, paradoksial terjadi karena awak redaksi media massa kian dituntut menjadi jurnalis multimedia–untuk tidak menyebut palugada (apa lu mau, gue ada)–namun tanpa disertai peningkatan signifikandari sisi apresiasi.
Jurnalis hari ini bukan hanya bisa meliput dan menuliskan dalam sebuah bentuk press klarr, akan tetapi diminta juga bisa membantu perluasan kanal medianya. Misal wartawan media cetak, juga dituntut mengirim format berita audio visual sekalipun isinya still video.
Atau ada pula kejadian, mereka juga harus membantu memublikasikan dari sisi media sosial akun kantornya sehingga pekerjaan berkali lipat.
Sayangnya, beban bertambah ini tak disertai dengan penghargaan layak yang sebetulnya tak selalu harus berbentuk honor.
Terakhir, paradoksial terjadi ketika peningkatan kapasitas daya beli sekaligus tingkat pendidikan masyarakat Indonesia beberapa tahun terakhir tidak berbanding lurus untuk menjadi faktor pendukung peningkatan kinerja sebuah media massa.
Dengan makin sejahtera dan kian terpapar pendidikan kian bagus, maka lebih banyak yang kemudian diinvestasikan dalam kepemilikan duniawi yang konsumtif alih-alih meningkatkan kapasitas ruhani dengan kepemilikan literasi dari media massa.
Sangat jarang yang kemudian berusaha berlangganan banyak media massa guna asupan intelektual mereka saat tingkat kehidupan mereka merambat naik.
Motor, mobil, rumah, tanah, dan aneka properti, dan terutama pelesir ke berbagai tempat sebagai bahan unggahan media sosial, terus jadi pilihan primer.
Karenanya, imbas preferensi tersebut, jangan kaget apalagi sewot, jika faktanya kemampuan literasi orang Jakarta dewasa (25-65 tahun) lulusan minimal sekolah menengah atas lebih rendah dari kemampuan literasi masyarakat Eropa tingkat sekolah dasar (OECD PIAAC, 2016).
Anomali-anomali inilah yang masih bergelayutan dalam HPN 2018 ini, sehingga media massa tak mudah menjadi rujukan utama masyarakat yang kini malah lebih gampang percaya berita bohong.
Sumber : Kompas.com