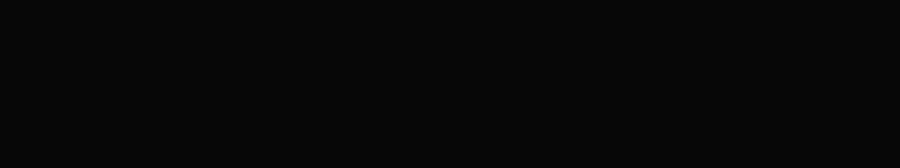BA Santamaria
TANGGAL 6 Desember 1975, beberapa jam setelah tentara Indonesia bergerak dalam invasi ke Timor Leste, Harry Tjan, salah seorang yang sangat tahu akan invasi ini makan malam di sebuah restoran di Hongkong. Bersamanya duduk dua orang Australia, BA Santamaria (akrab dipanggil ‘Bob’) dan Frank Mount. Ketiganya baru saja selesai menghadiri konferensi Pacific Insitute, sebuah lembaga yang didirikan atas ide dan inisiatif Santamaria. Frank Mount adalah operator Santamaria di Asia Tenggara.
Ketiga orang ini saling mengenal. Mereka adalah bagian dari jaringan ‘intelektual’ di Asia Tenggara. Yang menyatukan mereka adalah kesamaan pandangannya yang sangat anti komunis. Namun ada juga persamaan yang lebih mendasar, yang sangat penting dalam pembentukan pandangan anti-komunis mereka, yakni ketiganya adalah penganut Katolik. Katolisisme menjadi perekat utama mereka. Mereka bertemu secara reguler pada konferensi-konferensi Pacific Institute (PI) yang didirikan khusus untuk mendukung organisasi-organisasi anti-komunis di wilayah Asia Tenggara, khususnya di Vietnam Selatan, Filipina, dan Indonesia.
Acara makan malam ini diungkap Frank Mount dalam buku memoarnya yang berjudul “Wrestling with Asia: A Memoir.”[1] Buku ini bercerita tentang berbagai aksi yang dilakukan oleh penulisnya sebagai jurnalis, operator politik, dan agen intelijen swasta di berbagai negara di kawasan Asia Tenggara. Ditulis dengan gaya populer, buku memoar ini berusaha meramu sejarah, strategi, sedikit intrik, serta petualangan bergaya James Bond di Asia Tenggara. Dalam beberapa bagian, terkesan Mount melebih-lebihkan. Namun, ia juga mengungkap banyak hal dari sejarah yang dilihatnya dari perspektif pengalaman pribadi.
Petualangan Mount di Asia Tenggara berawal pada tahun 1967. Ketika itu, dia yang baru berusia 24 tahun, ditawari Bob Santamaria untuk melakukan perjalanan ke seluruh Asia Tenggara. Kepada Mount, Santamaria berkata, “Laporkan secara pribadi kepada saya tentang bagaimana kita bisa membantu kawan-kawan kita yang anti-komunis di sana, promosikan ide saya tentang Komunitas Pasifik (Pacific Community), dan kalau mau, tulis beberapa artikel di News Weekly (media yang diterbitkan Santamaria) dan untuk berbagai penerbitan.”
Itulah yang kemudian dilakukan oleh Frank Mount. Dia melakukan perjalanan ke Vietnam Selatan, Laos, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapore, Filipina, dan, tentu saja, Indonesia. Disamping melakukan reportase, dia juga membangun jaringan politik. Sebagaimana diungkap dalam memoar ini, Bob Santamaria membekali Frank Mount dengan satu hal yang paling penting dalam menjalankan tugasnya, yakni gereja Katolik dan kongregasi Serikat Yesus (Yesuit). Santamaria rupanya memiliki jaringan yang luas di kalangan Katolik, baik awam maupun klerikal, di wilayah ini. Jaringan inilah yang dipakainya memperluas agenda anti-komunisnya.
Buku memoar ini memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana sebuah kelompok di Australia memperluas jangkauan politiknya ke luar batas-batas negaranya dan membangun sekutu internasional. Kelompok ini berpusat pada diri Bob Santamaria, seorang politisi, organisator, komentator, dan intelektual yang memiliki pengaruh cukup besar di dalam dunia politik Australia. Pengaruhnya tetap terasa sekalipun dia sudah lama meninggal. Perdana Menteri Tony Abbott (2013-2015) kabarnya menganggap Santamaria sebagai mentor politiknya.
Jaringan Bob Santamaria di Indonesia berpusat pada sekelompok orang yang berada di lingkaran seorang imam Yesuit, Pater Josephus ‘Joop’ Gerardus Beek, SJ. Dia adalah figur yang sangat kontroversial, tidak saja didalam kongregasi Serikat Yesus (biasa disebut ‘Yesuit’ atau ‘Serikat’ saja), tapi di dalam gereja Katolik Indonesia, dan juga dalam sejarah politik negeri ini. Kiprah politiknya membuat dia seringkali berbenturan dengan hirarki gereja dan juga dengan rekan-rekannya sesama Yesuit serta imam-imam di luar Yesuit. Beberapa kali dia harus ‘diperiksa’ dan ‘diliburkan’ dari tugasnya. Namun pada saat itu, Beek memiliki jaringan kuat di lingkaran kekuasaan Soeharto. Keadaan ini menyulitkan pihak gereja Katolik dan Yesuit untuk mengambil tindakan keras karena khawatir akan menimbulkan berbagai kesulitan.
Pastur Katolik ini juga dikenal memiliki pusat pengkaderan yang dikenal dengan nama Khalwat Sebulan (Khasebul). Kelak, kader-kader hasil didikan Khasebul ini banyak yang menjadi operator-operator politik di bawah kendali asisten-asisten pribadi Soeharto, khususnya Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani. Mereka memiliki pengaruh yang amat besar pada masa-masa awal Orde Baru. Praktis merekalah yang menciptakan rancang bangun politik Orde Baru. Selain itu, mereka juga terlibat dalam dua peristiwa besar yaitu penentuan pendapat rakyat atau Pepera 1969 di Papua (lebih dikenal dengan nama Irian Jaya pada jaman Suharto) dan aneksasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia 1975.
Tulisan ini berusaha menelusuri jaringan yang dibangun Bob Santamaria di Indonesia, khususnya hubungannya dengan Pastur Beek, SJ dan lingkaran kader beserta operator-operator politiknya. Titik tolaknya adalah memoar yang ditulis Frank Mount dan kemudian membandingkan dengan beberapa memoar serta biografi yang terbit di Indonesia dan Australia. Informasi dari memoar tersebut sedapat mungkin dikonfirmasi dengan wawancara. Lebih dari tiga lusin orang telah diwawancarai untuk kepentingan artikel ini. Wawancara tersebut dilakukan entah untuk melakukan konfirmasi atau untuk menggali informasi baru.
Artikel ini ditulis sebagai informasi awal. Banyak hal didalamnya yang sulit dikonfirmasi, kecuali jika ada informasi dari arsip yang menguatkannya. Wawancara tidak banyak menolong karena sebagian besar dari mereka yang diwawancarai menolak untuk dikutip namanya sekalipun mereka memberikan informasi baru. Sebagaimana tentang topik yang menyangkut periode awal Orde Baru, dimana telah terjadi pembantaian besar-besaran yang mengakibatkan lebih dari setengah juta rakyat Indonesia meninggal, orang masih dihantui ketakutan untuk bicara.
Hubungan antara Pater Beek dengan Bob Santamaria menarik untuk ditelusuri. Kita tidak tahu sejak kapan persisnya hubungan ini dimulai. Namun, dari memoar Frank Mount, tampak bahwa keduanya sudah menjalin komunikasi sejak awal tahun 1960an. Pater Beek ketika itu sudah mengirimkan analisisnya tentang situasi politik Indonesia kepada Santamaria. Jaringan Santamaria agaknya menjadi satu-satunya akses Pater Beek ke dunia internasional.
Dengan demikian, di sini ada kemungkinan untuk membantah teori yang mengaitkan Pater Beek dengan CIA (Central Intelligence Agency, dinas intelijen milik Amerika Serikat). Sekalipun, bukan tidak mungkin hubungan dengan CIA itu terjadi lewat jalur Australia, khususnya lewat pengaruh jaringan Bob Santamaria yang sering meneruskan analisis yang dia dapat dari luar ke politisi dan lembaga-lembaga politik Australia. Tidak diragukan bahwa Santamaria juga memiliki koneksi ke dalam komunitas intelijen Australia, khususnya ke dalam Australian Secret Intelligence Service (ASIS). Besar kemungkinan analisis-analisis yang dikirimkan oleh Beek juga mendarat di meja analis-analis intelijen Australia. Pada gilirannya, karena adanya kerjasama dengan CIA, analisis dan informasi ini pun dibagi dengan CIA. Hubungan antara Beek dan CIA sangat jauh namun bukan tidak mungkin.
Apa yang terungkap dari hubungan antara Pater Beek dengan Bob Santamaria ini adalah adanya jaringan luas anti-komunis di Asia Tenggara. Jaringan itu tidak dikoordinasi oleh negara namun oleh individu-individu yang memiliki pengaruh politik di negaranya masing-masing. Mereka digerakkan oleh kesamaan ideologi anti-komunisme. Yang menarik, mereka juga berasal dari kelompok agama minoritas di Asia Tenggara – kecuali di Filipina – yakni Katolik.
Jurnalis, Petualang, Intel
Seperti Bob Santamaria, Frank Mount berasal dari Melbourne. Keluarga mereka pun saling berteman. Santamaria lebih merupakan figur bapak untuk Mount karena usia mereka yang terpaut jauh. Mount adalah anggota National Civic Council (NCC), sebuah organisasi anti-komunis yang didirikan oleh Santamaria. Mount juga menjadi pengurus beberapa organisasi sayap kanan. Dia pernah memimpin organisasi “Wheat for India” (1964-65) yang bertujuan untuk mengalihkan ekspor gandum Australia dari Cina Komunis ke India. Reputasinya sebagai orang sayap kanan cukup bagus.
Frank Mount juga seorang petualang. Dia sudah mengunjungi Asia sebelum direkrut oleh Santamaria. Selain itu, dia juga penyuka makanan enak, wine yang baik, dan tentu saja perempuan cantik. Dengan sedikit menyombong dia katakan bahwa petualangannya di Asia mirip seperti James Bond, bahkan ketika “James Bond belum ada dipikiran orang.”[2]
Tidak diragukan bahwa dia memiliki kapasitas sebagai seorang intel. Dia pandai bergaul dan cukup cepat menjalin pertemanan dan memengaruhi orang. Namun dia adalah juga seorang jurnalis, yang menulis selain untuk News Weekly, koran konservatif sayap kanan yang didirikan oleh Santamaria, juga menulis untuk koran-koran lain di Asia. Mount menyebutkan bahwa hampir semua tulisannya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh Kompas, sebuah koran Indonesia yang diasuh oleh orang-orang Katolik.[3]
Pada mulanya, tugas Mount di Asia Tenggara adalah mewujudkan gagasan Santamaria tentang Pacific Community. Dalam pikiran Santamaria, Pacific Community perlu dibentuk untuk menjaga kepentingan dan kelangsungan hidup Australia. Ini harus dilakukan dengan membendung pengaruh Cina Komunis, jalur perdagangan dan komunikasi antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, yang di tengah-tengahnya terdapat Laut Cina Selatan yang merupakan jalur ekonomi Australia, Jepang, Korea, dan negara-negara non-komunis lainnya. Untuk itu, Cina harus ditangkal pengaruhnya dan Indonesia harus dirangkul.
Untuk mewujudkan ide ini, dibentuklah Pacific Insitute (PI). Santamaria mengendalikan organisasi ini dari Melbourne, dan Frank Mount menjadi direktur pelaksana yang bergerak di lapangan. PI mengadakan pertemuan sekali dalam setahun. Pada awalnya, para peserta konferensi hanya saling bertukar informasi. Kemudian diharapkan agar para peserta, yang merupakan orang-orang yang berpengaruh di negaranya, akan merumuskan kebijakan untuk persoalan-persoalan yang dianggap penting. Mereka akan memengaruhi kebijakan dinegaranya masing-masing.
Frank Mount berkeliling ke Asia Tenggara untuk menyebarkan ide ini dan mencari peserta konferensi tahunan PI. Di Vietnam Selatan, dia bertemu dengan Kol. Ted Serong, yang juga adalah kawan dekat Santamaria. Saat itu Serong bekerja untuk CIA dalam program kontra-gerilya yang bernama ‘Phoenix Program.’ Program ini bertujuan untuk menghancurkan jaringan Vietcong di daerah pedesaan Vietnam Selatan dengan mengindentifikasi dan membunuh kader-kader kuncinya dan mengumpulkan data intelijen.
Walaupun diorganisasi oleh CIA, program ini sepenuhnya dijalankan dengan memakai organisasi keamanan lokal dan orang-orang lokal. Disinilah kemudian timbul masalah. Penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan terjadi dalam jumlah yang amat besar. Diperkirakan sekitar 60 ribu orang terbunuh oleh program ini. Sebagian besar dari mereka adalah guru dan tukang pos yang bekerja di pedesaan. Merekalah yang paling sering dijadikan sasaran karena dianggap sebagai kader kunci Vietcong.
Santamaria menjadikan Serong sebagai direktur nasional PI di Vietnam Selatan. Namun keterlibatan Santamaria di Vietnam Selatan tidak hanya terbatas pada PI. Dia juga memerintahkan Frank Mount untuk membantu penciptaan partai politik di sana. Terbentuklah Partai Nhan-Xa, yang merupakan bagian dari PI untuk mengembangkan ‘demokrasi liberal’ di wilayah Pasifik. Tidak hanya mendirikan partai politik, Santamaria juga membantu pembiayaan partai ini. Itu dilakukannya dengan mengalihkan sebagian dana dari Catholic Project Compassion yang seharusnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan sosial.[4]
Santamaria memberi satu jalur penting untuk mendulang informasi dari kawasan ini. Jalur itu adalah jaringan gereja Katolik, khususnya para uskup dan imam-imam Yesuit. Di Vietnam Selatan, Mount menjalin hubungan dengan uskup (kemudian menjadi kardinal) Mgr. Nguyen Van Thuan[5], yang adalah juga kemenakan Presiden Ngo Dinh Diem. Uskup Nguyen adalah orang penting di balik pendirian partai Nhan-Xa. Walaupun tidak menjadi anggota partai ini dia menjadi penyokong yang terpenting. Lewat Mount, Santamaria mengirimkan dana-dana yang dialihkan dari Catholic Project Compassion untuk Mgr. Nguyen Van Thuan, yang kemudian meneruskannya kepada kawan-kawannya yang anti komunis di Partai Nhan-Xa.[6]
Namun bagian terpenting dari koneksi Santamaria dan Frank Mount di Asia Tenggara adalah para Yesuit. Mount mengakui ini dan bahkan menulis satu bab khusus tentang Yesuit dalam memoarnya. Para Yesuit, tulisnya, telah memainkan peranan sangat penting dalam pembangunan lembaga-lembaga demokrasi liberal di wilayah ini. Mereka mendidik penduduk lokal yang non Katolik atau Kristen sesuai dengan prinsip-prinsip masyarakat sipil Barat yang modern. Mount mengutip seorang menteri di Indonesia yang dengan bangga mengatakan bahwa dirinya adalah seorang “Westernized Jesuit sufi Muslim.”[7]
Menurut Mount, paderi-paderi Katolik di Asia Tenggara adalah sumber informasi yang paling baik. Mereka adalah bagian dari lapisan tipis golongan terpelajar di kawasan ini. “Para misionaris asing dan paderi-paderi lokal sangat tahu akan apa yang terjadi secara politik, sosial dan ekonomi,’ tulisnya. Kemana pun dia pergi di seluruh kawasan ini, dia selalu mendatangi gereja Katolik dan jaringan klerikalnya serta membanding-bandingkan informasi yang dia dapat dari politisi, jurnalis, atau intelektual yang dia jumpai.
Konferensi pertama PI diadakan di Manila, Filipina, pada tahun 1967. Konferensi ini dihadiri oleh peserta dari Vietnam Selatan, Malaysia, Filipina, Srilanka, dan Indonesia. Peserta-peserta yang hadir sangat berpengaruh di negerinya masing-masing. Dari Vietnam, hadir Uskup Thuan dan para petinggi partai Nhan-Xa; beberapa politisi dan senator dari Filipina termasuk kepala dinas intelijen Filipina, dan seorang aktivis partai MCA (Malaysian Chinese Association). Beberapa Yesuit juga datang dalam konferensi pertama ini. Selain tuan rumah Pater Horacio de la Costa, SJ (yang kemudian menjadi Provinsial Yesuit Filipina), ada juga Pater Bill Smith, SJ dari Australia.
Peserta dari Indonesia tidak lain dan tidak bukan adalah Pater Joop Beek, SJ yang datang bersama Lim Bian Kie (yang kemudian dikenal dengan nama Jusuf Wanandi). Disinilah Frank Mount pertama kali bertemu dengan Beek yang datang atas undangan langsung dari Santamaria. Hubungan antara Beek dan Santamaria sudah terjalin jauh sebelum konferensi ini.
Mount baru menginjakkan kakinya di Jakarta pada tahun 1968. Walaupun sebelumnya dia telah sering membaca analisis-analisis tentang situasi di Indonesia yang diberikan kepadanya lewat Bob Santamaria. Analisis tersebut ditulis oleh Pater Beek dan dikirim kepada Bob Santamaria, yang kemudian “meneruskannya kepada intelijen Australia.”[8] Seperti yang sudah disebutkan, Beek sudah berhubungan dengan Santamaria jauh sebelum Mount menemuinya. Bahkan Beek sudah memperingatkan Santamaria akan adanya kemungkinan kudeta di Jakarta pada awal tahun 1960.[9]
Mount menjelajahi Jakarta dan Indonesia lewat Beek dan jaringannya. Ketika dia masuk ke Indonesia, anak-anak didik (protégés) dari Beek sudah menempati posisi-posisi strategis, khususnya dalam bekerja untuk Opsus (Operasi Khusus), sebuah lembaga intelijen tidak resmi yang dikendalikan oleh asisten pribadi Soeharto, Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani. Anak-anak didik Beek, yang dibinanya bertahun-tahun jauh sebelum dia mendirikan Khasebul (khalwat sebulan) yang terkenal itu, menjadi tulang punggung dari banyak operasi Opsus.
Beek memiliki jaringan kader yang luas di Jawa dan bahkan seluruh Indonesia. Para kader ini memberi laporan mingguan kepada Beek, yang berisi informasi dan data intelijen tentang apa yang terjadi di daerah masing-masing kader. Mereka disuruh melaporkan segala kegiatan organisasi politik dan keagamaan lokal, badan-badan pemerintahan, angkatan bersenjata dan kepolisian. Menurut Mount, semua informasi ini diteruskan kepada Ali Moertopo lewat Jusuf Wanandi dan kepada Soedjono Heomardani lewat Sofjan Wanandi (Liem Bian Koen). Mekanisme ini mengokohkan kekuasaan Ali Moertopo atas militer dan komunitas intelijen Indonesia. “Demikian bagusnya intelijen ini sehingga beberapa jendral menduga bahwa Moertopo pastilah menjalankan jaringan intelijen pribadinya, yang barangkali dilatih oleh CIA, di dalam tubuh militer,” demikian tulis Mount. [10]
Jika ke Jakarta, Beek menjadi tujuan pertama dari Frank Mount. Dia akan menemuinya entah di kantor “Biro” di Jl. Gunung Sahari atau di tempat kaderisasinya di bilangan Klender. Dalam pandangan Mount, Beek adalah seorang yang sangat anti komunis sekaligus sangat konservatif. Tujuannya melatih kader-kader kaum muda Katolik tidak lain daripada melindungi komunitas Katolik dan Kristen yang kecil. Pada awalnya dari ancaman Partai Komunis dan kemudian dari ancaman golongan Islam. Namun, sekalipun menjalani kehidupan yang sangat asketik sebagai Yesuit, Beek juga berpikiran liberal sebagaimana umumnya Yesuit yang berasal dari Belanda. Dengan sedikit menggoda, Mount menulis bahwa Beek “bisa sangat toleran pada mereka yang jatuh pada godaan daging,[11] yang jelas tidak masuk dalam bilangan dirinya sebagai pertapa dan orang biara.” Beek menyukai minuman keras terutama gin Bols Genever, yang menurut Mount barangkali pada akhirnya ikut membunuhnya. Selama bertahun-tahun dia membawakan Beek botol-botol buram itu “bersama dengan banyak, banyak ribuan dollar dari Santamaria dan teman-temannya.”[12]
Di Indonesia, Mount juga bergaul dengan banyak Yesuit yang lain. Di dalam memoarnya, dia mengutip laporannya kepada Santamaria tentang ‘kesaksian’ dari dua orang Yesuit tentang Beek. Yang pertama adalah Pater (Theodoor Willem) Geldorp, SJ atau yang lebih dikenal dengan nama Indonesianya, Dick Hartoko, SJ. Dia mengatakan Beek adalah seorang pemikir politik orisinal dan organisator yang baik, yang ‘menyelamatkan negeri ini lebih dari sekali.’ Sedangkan Pater Thomas Huber SJ memuji kecakapan kader-kader Beek, khususnya di Irian Barat.[13]
Barangkali yang mengenal nama Bartholomew Augustine (B.A.) Santamaria di Indonesia bisa dihitung dengan jari. Namun, seperti yang sudah kita lihat, Santamaria pernah memiliki sedikit pengaruh di dalam politik Indonesia. Paling tidak, dia secara tidak langsung memengaruhi politik Indonesia karena dukungannya terhadap Pater Joop Beek SJ dengan para kader dan anak didiknya.
Di negerinya, Santamaria adalah figur politik yang sangat berpengaruh. Selama lima dekade dia malang melintang mewarnai politik Australia, sekalipun tidak menduduki jabatan politik apapun atau bergabung dengan partai politik manapun. Banyak orang mengatakan bahwa dia adalah tokoh politik Australia terpenting di abad ke-20. Dia adalah figur yang penuh kontroversi, yang dipuja pendukungnya dan dicaci oleh penentangnya.
Bob Santamaria, demikian panggilan akrabnya, lahir di Melbourne pada 1915. Orangtuanya adalah imigran dari Italia yang bekerja sebagai pemilik toko. Santamaria menyelesaikan pendidikan dasarnya di kota ini. Ia juga belajar di Universitas Melbourne hingga jenjang Master.
Sejak masa mudanya, dia sudah menjadi aktivis. Masa kecilnya sebagai imigran Katolik yang umumnya adalah kelas bawah dalam strata sosial Australia ketika itu juga membentuk sikap politiknya. Terlebih lagi, pada saat itu gereja Katolik sedang mengalami transisi. Ketika dia berusia dua tahun, revolusi Bolshevik meletus di Rusia. Revolusi ini membawa gelombang sekularisme dan anti-agama di mana-mana. Di beberapa tempat, kekayaan gereja dipreteli. Banyak imam dan suster dibunuh.
Dua dekade sebelumnya, gereja Katolik juga dipaksa untuk merumuskan sikapnya menghadapi gelombang besar kapitalisme dan sosialisme. Tahun 1891, Paus Leo XIII mengeluarkan ensiklik Rerum Novarum yang pada intinya menolak ajaran sosialisme dan kapitalisme. Ensiklik ini mencoba membendung ekses-ekses buruk baik dari kapitalisme maupun sosialisme. Ia menawarkan jalan keluar dengan memberikan kontrak sosial yang menjamin hak-hak kaum buruh. Dengan demikian, Rerum Novarum berpisah dari kapitalisme dalam hal hak-hak kaum buruh, namun di sisi yang lain menangkal sosialisme yang berdasarkan perjuangan kelas, pertama-tama demi alasan karena sosialisme berdasarkan materialisme sekuler yang anti agama. Ini awal dari ajaran sosial gereja.
Santamaria dengan cepat mengambil bagian di dalamnya. Pada usia 26 tahun dia mendirikan surat kabar Catholic Worker. Pada penerbitan awalnya, koran ini sibuk memerangi ekses-ekses buruk dari kapitalisme dan berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Namun ini cepat berubah ketika Partai Komunis Australia (Communist Party of Australia atau CPA) juga mulai mengorganisir kaum buruh. Mulailah terjadi ketegangan antara kaum buruh yang diorganisir gereja Katolik dengan yang didukung oleh partai komunis. Pada tahun 1937, atas undangan Uskup Agung Melbourne, Mgr. Daniel Mannix, Santamaria bergabung dengan National Secretariat of Catholic Action, organisasi untuk kaum awam yang anti komunis.
Pada tahun 1941, Santamaria mendirikan Catholic Social Studies Movement atau yang di Australia dikenal dengan sebutan ‘The Movement” atau “The Grouper.” Ini adalah organisasi yang beroperasi secara rahasia atau setengah rahasia. Organisasi ini bersaing dengan CPA dalam mengorganisasi buruh di kantong-kantong industri Australia. Kehadirannya direstui dan bahkan disokong dengan dana oleh hirarki gereja Katolik.
Sekalipun bertarung sengit di lapangan, kedua organisasi ini tetap bernaung di bawah Partai Buruh (Labor Party) di Australia. Santamaria, yang didukung oleh kelompok-kelompok industrial, adalah sayap kanan dari partai ini. Namun setelah Perang Dunia II, khususnya ketika Perang Dingin mulai memanas, terjadi perpecahan di dalam Partai Buruh. Faksi kiri di dalam Partai Buruh menuduh Santamaria dan The Grouper sebagai penyebab kekalahan partai ini dalam pemilihan tingkat federal tahun 1954.
Perselisihan ini memuncak dan berakhir dengan didepaknya anggota parlemen yang berafiliasi pada Santamaria pada tahun 1955. Peristiwa ini dikenal sebagai ‘The Split’ dalam sejarah politik Australia dan akibatnya, dalam jangka waktu panjang, Partai Buruh tidak memenangkan pemilihan di tingkat federal. Santamaria kemudian membentuk Democratic Labor Party (DLP). Perpecahan dengan Partai Buruh ini juga mengakibatkan Santamaria kehilangan dukungan dari Gereja Katolik.
Tahun 1957, Santamaria mengubah Catholic Social Studies Movement menjadi National Civic Council (NCC). NCC juga memiliki corong sebuah suratkabar yang terbit secara berkala, News Weekly. Media ini tetap terbit secara teratur hingga sekarang. NCC sesungguhnya tidak berbeda dari The Movement. Ia tetap menjadi organisasi semi-rahasia. NCC juga bergerak lebih ke kanan dalam isu-isu sosial, seperti keyakinan akan keluarga sebagai dasar masyarakat, penentangan terhadap sentralisasi yang berlebihan, anti-aborsi, patriotisme, dan pemeliharaan nilai-nilai tradisi Judeo-Kristen.
Selain itu, Santamaria juga tampil di televisi dan memiliki show sendiri “Point of View.” Dia juga menjadi kolumnis di harian The Australian dan menulis komentar-komentarnya tentang situasi politik Australia.
Politik anti komunis membawa Santamaria ke Asia Tenggara. Partai Nhan-Xa yang dibentuk di Vietnam Selatan atas bantuannya didasarkan atas model Democratic Labor Party di Australia. Dia juga menciptakan jaringan elit-elit dari berbagai negara Asia Tenggara dan menciptakan sebuah lembaga yang bernama Pacific Institute. Sama seperti di Australia, para elit ini adalah elit-elit Katolik yang memiliki peranan dalam politik dinegaranya masing-masing.
Yang menarik adalah di Indonesia, dimana jaringan Santamaria bertumpu pada Pater Joop Beek, SJ dan anak-anak didiknya. Hingga di sini, kemudian muncul pertanyaan: Mengapa Santamaria memilih Pater Joop Beek, SJ dan kelompooknya? Sejak kapan sesungguhnya mereka saling mengenal? Apakah mereka pernah bertemu sebelum konferensi-konferensi yang diorganisir Pacific Institute?
Sebagian besar dari pertanyaan-pertanyaan tersebut sulit untuk dijawab secara langsung. Mungkin kalau arsip-arsip Santamaria diselidiki lebih lanjut akan didapat jawaban. Arsip-arsip ini disimpan di State Library of Victoria, Australia, dan pihak keluarga Santamaria sudah menetapkan bahwa arsip-arsip itu tidak bisa dibuka sampai 40 tahun setelah kematian Santamaria di tahun 1998. Walaupun demikian, pihak keluarga memberikan perkecualian kepada Patrick Morgan untuk menerbitkan dan menjadi editor sebagian kecil dari surat-surat Santamaria yang kemudian terbit dibawah judul “Your Most Obedient Servant.” Dari buku ini kita tahu bahwa Santamaria sudah menjalin korespondensi dengan Pater Beek sejak awal tahun 1960an dan mungkin juga jauh sebelum itu.
Sesungguhnya ada banyak persamaan antara Santamaria dan Beek dalam hal pandangan ideologis mereka dan cara-cara mereka membangun organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan ideologis mereka. Bila diletakkan dalam konteks sejarah, pandangan ideologis Santamaria dan Beek ini sebenarnya adalah pandangan umum dan sikap gereja Katolik terhadap politik pada saat itu.
Seperti Santamaria, Beek juga pernah mengorganisir kaum buruh dan tani untuk menyaingi serikat buruh tani milik PKI (SOBSI dan BTI). Bersama dengan kawan seangkatannya di Yesuit, John (Johannes Baptista) Dijkstra, SJ, Beek pernah mendirikan Gerakan Pancasila[14] yang melahirkan Ikatan Buruh Pancasila, Ikatan Petani Pancasila, Ikatan Para-Medis Pancasila, dan Ikatan Usahawan Pancasila. Untuk waktu yang cukup lama, Beek menjadi moderator dari Ikatan Buruh Pancasila.
Namun Beek, seperti yang akan kita lihat di bawah ini, memutuskan untuk memusatkan perhatian pada kaderisasi. Pola yang dipakai pun mirip dengan pola The Movement, dan kemudian NCC, yang didirikan Santamaria. Sama seperti Santamaria, kaderisasi yang dilakukan oleh Beek – baik pada periode sebelum dan sesudah Khasebul – dipenuhi dengan kerahasiaan. Kader-kader ini kemudian ditanamkan atau menyusup ke organisasi-organisasi lain untuk memengaruhi pencapaian tujuan ideologis mereka.
Pastur Misterius Pencetak Kader
Josephus Gerardus Beek lahir di Amsterdam pada tahun 1917. Dia hampir seumuran dengan Santamaria. Seperti Santamaria, dia juga berasal dari kalangan kelas menengah bawah. Dia menghabiskan masa kecilnya di kota Amsterdam. Pada usia 18 tahun, dia memasuki ordo Serikat Yesus sebagai novis (calon imam). Dua tahun kemudian dia dikirim ke tanah misi di Jawa. Namun sayang, pada tahun 1942 kekuasaan pemerintah kolonial Belanda runtuh akibat pendudukan Jepang. Beek, sebagaimana orang Belanda lainnya, ditahan di kamp interniran. Dia baru dibebaskan empat tahun kemudian.
Sebagai bagian dari formasi imamatnya, Beek menempuh studi teologinya di Maastricth, Belanda pada tahun 1947 hingga 1950. Dia ditahbiskan menjadi imam Katolik pada Desember 1948. Setelah menerima licentiat dalam studi teologinya, Beek pergi ke Inggris untuk menjalani masa Tersiat. Ini adalah tahap terakhir dari proses yang harus dilalui sebelum seseorang menjadi anggota penuh dari Serikat Yesus.
Dia kembali ke Indonesia pada tahun 1952 dan bekerja sebagai pamong (perfect)[15] di Seminari (sekolah pendidikan calon imam Katolik) Menengah Kanisius di Jl. Code 2, Yogyakarta (kini Kolose St. Ignatius). Belum setahun bekerja di Seminari, Beek dipindah dan diberi tugas untuk membangun sebuah asrama untuk mahasiswa.
Itulah Asrama Mahasiswa Realino. Beek membangun asrama ini tidak saja secara fisik namun juga meletakkan ide dasar pengembangannya. Asrama ini dibangun secara fisik sebagai bangunan asrama modern pada masanya – dengan dapur, ruang makan, ruang studi, ruang rekreasi, kamar tidur, dan lapangan olahraga untuk lebih dari 250 mahasiswa. Ide dasar dari Beek adalah bahwa asrama ini hanya untuk mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada yang memiliki ‘bakat dan kemampuan intelektual tinggi.’[16] Yang menarik adalah bahwa penghuni asrama ini tidak dibatasi untuk mereka yang Katolik saja namun terbuka bagi mahasiswa dari agama-agama lain. Para mahasiswa juga dibekali ketrampilan berorganisasi, dilatih berdiskusi, dan berbicara di depan umum (public speaking).
Ahmad Wahib, seorang intelektual pembaharu pemikiran Islam, pernah tinggal di asrama ini antara tahun 1961-1964. Saat itu, Beek sudah tidak lagi mengasuh asrama ini dan sudah pindah ke Jakarta. Tahun 1960an itu adalah tahun-tahun kejayaan asrama ini. Namun, dalam perkembangannya kemudian, semakin sedikit mahasiswa dari agama lain (khususnya yang Muslim) yang mau tinggal di Asrama Realino. Demikian pula kekhususan untuk mahasiswa Universitas Gadjah Mada juga tidak dapat dipertahankan. Sejak tahun 1980an, asrama ini dihuni mayoritas mahasiswa Katolik dan kualitasnya pun merosot. Tahun 1991, asrama mahasiswa ini ditutup untuk selamanya dan gedung-gedungnya dimanfaatkan untuk gedung kuliah Universitas Sanata Dharma dan sebagian kecil untuk sebuah lembaga riset, Lembaga Studi Realino.
Selain mengasuh Realino, Beek juga menjadi moderator PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia). Pada saat itu, PMKRI masih berupa perserikatan dari empat cabang yang ada di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Ketua organisasi ini dijabat bergiliran oleh cabang-cabang. Beek menjadi moderator cabang Yogyakarta.
Pada tahun 1959, Beek dipindahkan ke Jakarta. Kabarnya dia dipindahkan karena keluhan dari sesama Yesuit yang kesulitan bekerjasama dengannya. Pribadi Beek yang keras dan cenderung arogan serta mau menang sendiri untuk tujuan sendiri menimbulkan benturan dengan sesama Yesuit.
Di Jakarta, Beek diangkat menjadi Sekretaris Nasional Konggregasi Maria atau yang secara internasional lebih dikenal sebagai Sodality of the Blessed Virgin Mary. Ini adalah sebuah perkumpulan yang didirikan oleh seorang Yesuit Belgia, Jean Leunis, SJ, pada tahun 1563. Perkumpulan ini mencoba untuk menghayati kehidupan spiritual yang diajarkan oleh pendiri ordo Serikat Yesus, St. Ignatius dari Loyola. Anggotanya sebagian besar adalah orang-orang awam.
Di tangan Beek, Konggregasi Maria berubah dari sebuah perkumpulan spiritual[17] menjadi lebih ‘intelektual.’[18] Dia membentuk Konggregasi Maria untuk para sarjana,[19] mahasiswa, dan mereka yang sudah bekerja namun bukan sarjana. Kelompok ketiga ini disebutnya sebagai kelompok Pemuda Karya (sic). Rekrutmen untuk anggota-anggota Konggregasi Maria dilakukan lewat paroki-paroki. Namun ada sumber penting lain untuk mendapatkan kader-kader yang lebih ‘intelek.’ Beek memiliki akses ke organisasi mahasiswa ekstra kampus seperti PMKRI dan Pemuda Katolik. Kedua organisasi ini merupakan lahan subur untuk merekrut anggota.
Dari sinilah sesungguhnya Beek mengembangkan metode-metode pelatihan. Sekalipun dibungkus dengan metode Latihan Rohani Ignatian yang khas Yesuit, tujuan dari pelatihan-pelatihan ini lebih untuk melatih militansi, membentuk kader, menyusun organisasi, dan membuat mekanisme ‘pelaporan situasi’ yang bekerja mirip seperti sistem intelijen dimana Beek mengendalikan para kader ini.
Pada tahun-tahun inilah, seperti yang sudah kita ketahui, Beek menjalin hubungan dengan B.A. Santamaria di Australia. Kita tidak tahu apakah mereka pernah bertemu. Tapi setidaknya mereka melakukan korespondensi dan, seperti yang disebutkan oleh Frank Mount dalam memoarnya, banyak analisis yang sampai kepada Santamaria dikirim lewat saluran-saluran Yesuit.
Ketika menjalankan Konggregasi Maria, Beek sudah menerapkan latihan-latihan yang disebutnya khalwat – yang artinya pengasingan diri atau ‘retreat’ — untuk para sarjana dan mahasiswa. Khalwat ini diberikan dalam waktu sebulan. Pesertanya datang dari seluruh Indonesia. Rekrutmen dilakukan lewat paroki-paroki.[20] Bahkan saat mengurus Konggregasi Maria, Beek tidak lepas dari kontroversi yang mendatangkan keluhan dari sesama Yesuit. Pada tahun 1960, provinsial Yesuit memutuskan bahwa Beek harus mengambil sabbatical selama setahun. Dia dikirim ke Inggris untuk belajar psikologi anak-anak nakal.[21]
Pada tahun 1961, Provinsial Serikat Yesus Indonesia membentuk sebuah biro yang dinamakan Biro Dokumentasi. Biro ini pada awalnya dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada para uskup Katolik Indonesia tentang situasi sosial dan politik di Indonesia. Beek yang baru pulang dari Inggris diserahi tugas untuk memulai biro ini, disamping tugasnya sebagai moderator Konggregasi Maria.
Di tangan Beek, Biro Dokumentasi ini beroperasi lebih mirip seperti sebuah think-tank ketimbang sebuah lembaga yang memberikan informasi untuk para uskup. Y.B. Soedarmanta, yang menulis biografi Pater Beek, menyebutkan bahwa biro ini “menyediakan bahan-bahan studi dan analisis keadaan berdasarkan tolok ukur ajaran dan moralitas Katolik agar dapat dipergunakan bagi para aktivis yang terlibat dalam organisasi kemasyarakatan.”[22]
Biro ini memiliki staf tiga orang sarjana yang bekerja penuh dan empat sarjana lain yang bekerja paruh waktu. Mereka bertugas mendokumentasi koran dan membuat ringkasan berita. Mereka juga melacak opini dan membuat semacam data-base para tokoh politik dan mengidentifikasi pandangan-pandangan politik mereka. Biro ini juga secara periodik mengeluarkan analisis-analisisnya yang tidak saja disebarkan di dalam negeri namun juga untuk konsumsi internasional dan berbahasa Inggris.
Biro Dokumentasi sengaja dibiarkan tumpang tindih dengan Konggregasi Maria. Ini pertama-tama dimaksudkan untuk “mendapatkan sumber tenaga yang bersemangat apostolis[23] … yang sadar akan kerasulan intelektual. “ Kedua, dengan menyamarkan biro ini di balik kegiatan religius maka akan “dihindarkan cap “terlalu politik” dengan ancaman bahwa usaha ini bisa dibreidel atau diganyang dengan mudah atau dibubarkan begitu saja. Sedangkan alasan ketiga adalah Biro Dokumentasi tidak bisa diasosiasikan langsung di bawah hirarki gereja karena ia hanya bernaung di bawah kelompok spiritual yang tidak ada hubungan apapun dengan hirarki gereja.[24]
Banyak orang menyamakan kegiatan Pater Beek ini dengan kegiatan seorang Yesuit keturunan Hungaria di Hongkong. Yesuit tersebut adalah Pater László Ladány, SJ pengamat masalah-masalah Cina. Pada tahun 1949, Ladány harus keluar dari Cina daratan setelah kemenangan Partai Komunis Cina (PKC). Dia menetap di Hongkong. Dari daerah protektorat Inggris ini dia mulai mengamati Cina dengan memonitor surat kabar dan majalah yang terbit di daratan serta meneliti dokumen-dokumen dari pejabat PKC. Namun yang terpenting adalah dia mendengarkan siaran radio, terutama dari daerah-daerah.
Pater Ladány menerbitkan China News Analysis pada 1953. Terbitan ini dengan segera menarik perhatian jurnalis, akademisi, peneliti, analis intelijen dan think tank, serta mereka yang menaruh perhatian terhadap masalah Cina. China News Analysis ini terbukti dapat melihat dengan tepat apa yang terjadi di Cina. Seperti misalnya, Ladány secara tepat menunjukkan terjadinya kelaparan hebat di daerah-daerah pedesaan Cina semasa Revolusi Kebudayaan.
Analisis Ladány yang sangat kritis terhadap Cina membuatnya mendapat cap ‘fanatik anti Komunis.’ Ini adalah cap yang bukan tidak lazim dikenakan terhadap Yesuit dan pada gereja Katolik pada saat itu. Seperti yang kita lihat di atas, gereja Katolik memang sangat anti komunis.
Kita tidak tahu apakah Pater Ladány mengenal BA Santamaria dan jaringannya. Sebenarnya tidak terlalu aneh kalau mereka saling mengenal karena sama-sama anti komunis. Konferensi Pacific Institute juga beberapa kali diadakan di Hongkong. Demikian pula, apakah ada hubungan antara Ladány dengan Beek? Buku memoar Yusuf Wanandi (Liem Bian Kie), salah seorang sekondan terdekat Beek, menulis bahwa Yusuf Wanandi kerap mengunjungi Pater Ladány kalau dia singgah di Hongkong.
Hanya saja, ada satu perbedaan besar antara Beek dan Ladány. Pater Ladány hanya bekerja sepenuhnya untuk China News Analysis. Dialah satu-satunya editor terbitan ini. Sehingga ketika dia memutuskan untuk berhenti maka berhenti pulalah penerbitan China News Analysis. Sedangkan Beek tidak membatasi dirinya hanya sekedar melakukan analisis seperti yang dilakukan oleh Ladány. Dia merekrut dan melatih kader-kader dan kemudian menciptakan sistem untuk mengontrolnya.
Pada akhir tahun 1966, Beek memulai program Khasebul (Khalwat Sebulan) yang pesertanya khusus mahasiwa. Ini meneruskan program kaderisasi yang sudah dia lakukan di dalam Konggregasi Maria. Hanya saja, pesertanya dibatasi pada mahasiswa saja. Tidak terlalu jelas apa alasan yang membuat Beek mengeluarkan program kaderisasi ini dari Konggregasi Maria.
Kemungkinan pertama adalah ‘persoalan’ antara Beek dengan ordonya sendiri dan dengan imam-imam di berbagai paroki. Biografi yang disusun oleh JB Soedarmanta memuat satu peristiwa yang terjadi pada tahun 1966. Disebutkan bahwa Beek diperiksa oleh Asisten Jendral Jesuit Pater Vincent O’Keefe yang sedang berkunjung ke Asia, termasuk Indonesia. Beek diperiksa berkaitan dengan metode pendidikan anak-anak muda yang dia lakukan. Agaknya, Jendral Jesuit di Roma mendengar bagaimana Konggregasi Maria tidak lagi semata-mata menjadi perkumpulan spiritual. Pada tahun 1967, Konggregasi Maria diubah menjadi Christian Life Community (CLC) dan fungsinya dikembalikan sebagai lembaga rohani.
Yang kedua adalah perkembangan politik. Kita tahu, kudeta gagal G30S dilancarkan setahun sebelumnya. Setelah itu, terbentuk aliansi antara mahasiswa – yang banyak dimotori dan dikendalikan oleh kader-kader Beek – dengan militer. Khasebul tampaknya adalah upaya untuk melatih mahasiswa yang diperlukan untuk menyokong Orde Baru yang baru saja berdiri itu.
Bagaimana Khasebul dijalankan?
Soedjati Djiwandono, salah seorang anak didik Beek pernah menulis sekilas tentang metode pelatihan Beek di Mingguan Hidup Katolik. Menurut Soedjati, program Khasebul dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan Kaderisasi Dasar (Kadas), yang berlangsung seminggu. Pesertanya sekitar 20 orang. Pembimbingnya adalah kader Khasebul senior. Terkadang kadas ini juga didampingi oleh Pastur Paroki atau bahkan Pater Beek sendiri. Materi Kadas adalah hal-hal yang mendasar seperti demokrasi, ormas, dan organisasi politik (orpol). Dari peserta Kadas inilah direkrut peserta Khasebul. Umumnya, Khasebul diikuti oleh 30 orang yang dipilih dari berbagai daerah di Indonesia.[25] Khasebul dilakukan empat kali dalam setahun.
Pendidikan di dalam Khasebul terkenal sangat keras. Para peserta dituntut berdisiplin sangat tinggi. Mereka diajarkan organisasi, berbicara di depan umum (public speaking), melakukan analisis dan menulis laporan. Mereka juga mendengarkan ceramah-ceramah yang disampaikan oleh elit-elit Katolik (bahkan yang sederajat menteri) dan intelektual.
Peserta juga harus berefleksi terhadap kelemahan-kelemahannya sendiri dan berusaha mencari jalan keluar dari kelemahan itu. Beek sendiri juga turun tangan dalam mengevaluasi kelemahan-kelemahan pribadi para peserta. Sanksi disiplin sangat keras. Setiap pelanggaran dikenakan hukuman dan sering hukuman itu adalah hukum fisik seperti ditempeleng.[26] Tidak jarang pula peserta dipulangkan sebelum menyelesaikan pendidikan. Baik mereka yang selesai menjalani kaderisasi maupun yang dikeluarkan di tengah jalan tidak akan pernah berbicara tentang Khasebul. Sama seperti NCC dari Bob Santamaria, kader-kader hasil pendidikan Khasebul menjadi mirip seperti sebuah ‘secret society.’ Kultur kerahasiaan ini menjadi ciri khas kader-kader Beek. Mereka tidak pernah berbicara tentang kaderisasi atau proses kaderisasi. Namun, di dalam gereja Katolik, kadangkala orang mudah mengidentifikasi orang-orang Khasebul karena keaktifan mereka berbicara politik dan jaringan yang mereka miliki dengan elit-elit Katolik tingkat nasional.
Dengan metode ini, Beek percaya bahwa dia akan mampu membentuk karakter peserta Khasebul. Selain pembentukan kepribadian, dia juga ingin memperkuat mereka secara rohani. JB Soedarmanta menguraikan dengan panjang lebar ‘kualitas’ seorang kader. Mereka diharapkan menjadi orang yang mengenal dirinya sendiri, pemberani, dan ‘rela memanggul salib’ – yang artinya sanggup menderita untuk orang lain. Menurut Soedjati Djiwandono, Beek tidak menentukan masa depan kadernya. “Mereka akan diperlukan dalam segala bidang kehidupan di masyarakat. Yang penting adalah keyakinan imannya dan keahlian dalam bidangnya sendiri,” demikian tulis Djiwandono.
Beek sendiri aktif mengekspresikan pandangan-pandangan politiknya kepada khalayaknya sendiri. Menurut Soedjati Djiwandono, Beek aktif menggelar diskusi setiap Jumat malam di tempat yang berpindah-pindah, kadang di Keuskupan, di Gedung KWI, atau di gedung sekolah Katolik. Mereka yang hadir adalah pengajar Khasebul, para kader, para pastor, bahkan uskup Jakarta, Mgr. Djajaseputra, SJ, serta tokoh-tokoh politik Katolik. Beek menyampaikan ‘evaluasinya’ terhadap masalah-masalah aktual.
Hasilnya ditulis dalam selebaran satu lembar yang diberi nama “Evaluasi.” Selebaran ini disebar ke berbagai pihak, termasuk surat-surat kabar. Menurut Djiwandono, kadang evaluasi ini “isinya satu-dua kali dimuat di majalah Times.[27] Penulisnya adalah Beek sendiri, tapi kadang juga ditulis oleh kader-kader senior seperti JB Oetoro, Haksoro, Kadjat Hartojo, Soedrajad Djiwandono[28], atau Soedjati Djiwandono sendiri. Tentu saja, Beek menjadi pemeriksa akhir dari naskah yang ditulis para kader ini. Beek juga mengeluarkan publikasi dalam bahasa Inggris Monthly Review, yang terbit sekali dalam sebulan
Dominasi Ideologi Kanan
Apakah yang menggerakkan Beek untuk membentuk kaderisasi ini? Tidak terlalu sulit untuk memahaminya. Sikap politik Beek sesungguhnya adalah sikap politik gereja pada waktu itu dalam menanggapi pergolakan-pergolakan politik. Ketika dihadapkan pada gelombang persaingan dua ideologi besar antara kapitalisme dan sosialisme, Gereja Katolik menolak keduanya. Gereja memilih untuk berpihak kepada buruh namun tidak dalam kerangka Marxisme. Sikap inilah yang juga diambil oleh BA Santamaria di Australia dan oleh politisi-politisi Katolik di banyak tempat di belahan dunia.
Namun ideologi yang diturunkan dari ajaran sosial gereja ini juga bisa memantik gerakan sosial yang berbeda. Di Amerika Serikat muncul gerakan Catholic Worker Movement yang digerakkan oleh Dorothy Day, seorang aktivis sosial yang menganut Katolisisme pada usia dewasa setelah sebelumnya hidup secara bohemia. Dorothy Day adalah penganjur distributisme, sebuah sistem ekonomi yang berasal dari ajaran sosial gereja, yang menolak dalil-dalil sosialisme dan kapitalisme. Prinsip-prinsip distributisme ini hampir mirip dengan yang diterapkan oleh Catholic Social Studies Movement yang didirikan oleh BA Santamaria pada tahun 1940an. Bedanya adalah Santamaria pada akhirnya bergerak ke kanan, sementara gerakan Dorothy Day di Amerika menjadi peletak dasar-dasar pasifisme, yang nantinya akan menjadi gerakan anti perang, khususnya anti Perang Vietnam tahun 1960-70an.
Permasalahan muncul ketika bangkit fasisme di Eropa. Ideologi ini sangat populer di kalangan kaum buruh dan kelas menengah bawah yang menginginkan pemimpin yang kuat. Para politisi Katolik dan hirarki gereja Katolik sendiri banyak yang tergoda dengan fasisme, terutama karena fasisme menolak liberalisme, Marxisme, dan anarkisme. Paus Pius XII, yang bertakhta sebelum dan selama Perang Dunia II, tidak menunjukkan sikap yang tegas terhadap fasisme baik di Italia (fasisme Mussolini) maupun di Jerman (Hitler). Sikap ini di kemudian hari dianggap sebagai dukungan terhadap fasisme.
Di Australia, BA Santamaria tidak menyembunyikan simpatinya kepada fasisme. Dia pernah berceramah mempertahankan Jenderal Franco, seorang jenderal fasis yang memerintah Spanyol dari tahun 1939 hingga 1975. Santamaria juga menulis tesis tentang Mussolini. Di kemudian hari, Santamaria menyangkal bahwa dia pernah mendukung fasisme.
Tidak pelak, ajaran sosial gereja dengan segala ramifikasi ideologisnya itu lah yang memengaruhi Pater Beek. Imam Yesuit ini tampaknya lebih dekat ke pemikiran Santamaria yang anti komunis itu. Ideologi yang cenderung ke kanan ini juga menjelaskan mengapa Beek sangat mudah menjalin persekutuan dengan tentara. Sekalipun tidak ada bukti bahwa Beek berhubungan langsung dengan tentara dan Soeharto, tidak dapat dipungkiri bahwa kader-kader terdekatnya bekerja untuk Soeharto atas restu dan berkat dari Beek.
Tidak terlalu sulit untuk mengerti bahwa ideologi politik kanan ini juga dekat dengan fundamentalisme keagamaan.[29] Dalam hal ini, ketika dihadapkan pada pilihan apakah bekerja sama dengan tentara atau dengan golongan Islam, kader-kader Beek kemudian memilih yang pertama. Mereka mempopulerkan prinsip ‘minus malum’ atau ‘the lesser of two evils’ yakni sebuah sikap untuk mengambil yang paling kurang keburukannya ketika dihadapkan pada dua pilihan buruk.
Prinsip ini diterapkan ketika golongan Katolik dalam masa transisi setelah kejatuhan PKI dan pemerintahan Presiden Sukarno harus memilih dengan siapa harus beraliansi. Kader-kader Beek mendefinisikan situasi pilihan ketika itu adalah antara berpihak pada militer atau kepada golongan Islam. Pilihan jatuh pada aliansi dengan pihak militer.
Sesungguhnya, dalam kenyataan ada plihan yang lebih luas yakni antara militer dan golongan sipil yang lebih luas (tidak hanya golongan Islam saja). Kader-kader Beek, karena dorongan fundamentalisme keagamaan, dengan tanpa ragu memilih beraliansi dengan militer. Segolongan kecil politisi Katolik yang pernah bergabung dengan aliansi Liga Demokrasi[30] menginginkan keadaan kembali seperti jaman Demokrasi Liberal. Namun suara mereka tenggelam karena dominannya kekuatan kader-kader Beek di dalam golongan Katolik. Puncaknya adalah ketika Partai Katolik dibubarkan pada tahun 1972.
Menghancurkan PKI: Satu Selimut Dengan Orde Baru
Kaderisasi oleh Beek dilakukan dalam waktu yang amat panjang. Dia sudah mulai bekerja di antara mahasiswa sejak 1952. Beberapa kadernya yang paling dekat direkrutnya jauh sebelum dia mendirikan Khasebul. Harry Tjan, misalnya, mengenal Beek sejak tahun 1953 saat masih duduk di bangku SMA. Dia bertemu Beek dalam sebuah retret untuk anak-anak SMA De Britto, Yogyakarta. Harry Tjan kemudian aktif di PMKRI dan akhirnya menjadi Sekretaris Jendral Partai Katolik, partai yang dibubarkan pada tahun 1972.
Tidak banyak diketahui bagaimana cara bergerak kader-kader Beek yang dilatih lewat berbagai lembaga seperti Realino, PMKRI, Konggregasi Maria, dan Biro Dokumentasi. Namun ada sedikit keterangan dari buku memoar Yusuf Wanandi, Shades of Grey,[31] yang terbit pada 2012. Sekalipun Wanandi bercerita terus terang tentang banyak hal yang tidak diketahui umum tentang masa-masa Orde Baru, buku memoar ini memiliki satu lubang besar. Itu adalah Pater Joop Beek, SJ. Wanandi tidak sekalipun menyebut nama Beek dalam bukunya ini. Sekalipun pastur Yesuit ini memiliki peranan amat penting dalam awal-awal perjalanan karirnya dan dalam hidupnya.
Wanandi juga menyebut cikal-bakal CSIS (Center for Strategic and International Studies) tanpa terang-terangan menyebut nama Biro Dokumentasi yang dikelola oleh Beek. “Cikal bakal dari apa yang nantinya akan menjadi Center for Strategic and International Studies – yang menjadi fokus dari kehidupan profesional saya – adalah sebuah rumah kecil di Jalan Gunung Sahari dekat Pasar Baru.”[32] Kita tahu bahwa ini adalah sebuah rumah di Jl. Gunung Sahari No. 88 yang dulu menjadi kantor Biro Dokumentasi. Tidak diketahui sejak kapan Biro Dokumentasi dibubarkan.[33]
Memoar Wanandi mengungkap beberapa aspek penting dari politik Katolik menjelang tahun 1965. Disamping secara intensif melakukan pengkaderan, Biro Dokumentasi juga melakukan analisis terhadap situasi. Wanandi menulis bahwa para intelektual dan mahasiswa Katolik secara serius mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi seandainya dalam waktu lima tahun PKI berkuasa. Wanandi menulis, “Dan, kami sebagai orang Katolik tahu bahwa kamilah yang pertama-tama harus menghadapi regu tembak (first up against the wall). Kami bisa mengelak dari Sukarno karena dia perlu minoritas seperti kami. Kami membuka kesempatan bagi dia untuk menunjukkan bahwa pemerintahannya bukanlah pemerintahan komunis. Namun ini juga alasannya PKI menjadi paling membenci kami.”[34]
Tidak banyak orang yang tahu bahwa kelompok Katolik ini sudah mempersiapkan segalanya untuk mengantisipasi kekuasaan PKI. Wanandi menulis bahwa generasi muda Katolik sangat bersemangat. Mereka juga bersiap untuk bergerak di bawah tanah jika keadaan menuntut. Mereka memiliki antara 2000 hingga 3000 orang kader politik yang terlatih. Kader-kader ini dilengkapi dengan mesin-mesin ketik, kertas, dan mesin stensil untuk mencetak selebaran.[35] Mereka juga sudah menyiapkan tempat-tempat persembunyian jika keadaan membutuhkan.
Yang paling menarik dari paparan Wanandi ini adalah pengakuannya bahwa mereka memiliki ‘senjata rahasia.’ Dia menulis, “Di jajaran petinggi PKI kami memiliki seorang informan, seorang anak muda lulusan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, yang pada tahun 1958, kawin dengan seorang Katolik dan kemudian pindah agama. Anak muda ini sudah menjadi anggota CGMI[36] dan ketika dia memberitahu kami akan rencananya untuk pindah agama, kami katakan padanya untuk tidak memberitahu siapapun. Kami minta dia untuk melaporkan kepada kami apa yang dia lihat dan dengar. Anak ini sangat pintar, sehingga PKI dengan cepat mempromosikan dia, dan pada awal tahun 1960an mereka membawa dia ke Jakarta, dimana dia selama tiga tahun ditempatkan di Sekretariat (PKI, red.), sebelum menjadi pembantu Sudisman, orang penting nomor empat di PKI dan juga Sekretaris Jendral partai ini. Dan, anak muda pemberani ini – yang namanya masih terlalu sensitif untuk diungkap – membuat kami mampu mengikuti apa yang sedang terjadi (didalam tubuh PKI, Red.).”[37]
Sangat jelas di sini bahwa Beek juga memiliki kemampuan untuk melakukan infiltrasi, bahkan ke jantung PKI. Dari korespondensi dengan BA Santamaria, kita tahu bahwa Beek sudah memperingatkan Santamaria akan adanya kemungkinan kudeta oleh PKI sejak awal tahun 1960an. Dengan memiliki informan yang ditanam di Sekretariat PKI dan bahkan menjadi pembantu Sudisman, tentu Beek mendapatkan informasi yang cukup akurat tentang PKI.
Usaha untuk menyingkap siapa orang ini tidak menemui hasil. Saya menghubungi Tan Swie Ling yang juga menjadi salah satu pembantu Sudisman pada saat itu. Tan Swie Ling pun tidak tahu menahu akan adanya informan ini. Demikian pula beberapa bekas anggota CGMI di Universitas Gadjah Mada, semuanya tidak bisa mengidentifikasi orang yang diklaim Wanandi ini.
Apapun yang terjadi, yang jelas Beek dan Biro Dokumentasinya memiliki database yang sangat bagus tentang elit Indonesia pada saat itu. Seperti yang telah disebutkan di atas, mereka dengan sangat rajin mencatat nama-nama serta pandangan politik para elit di Jakarta. Tidak dapat disangkal bahwa Beek dan Biro Dokumentasinya adalah kelompok yang paling tahu (well-informed) tentang PKI.
Kemungkinan ini juga mengandung pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Apakah Beek dan Biro Dokumentasinya pernah membuat daftar para elit PKI – kelompok politik yang mereka anggap sebagai musuh utama mereka? Jika pernah, kemanakah daftar ini dibagikan? Apakah Santamaria pernah menerimanya? Dari Frank Mount kita tahu bahwa Santamaria biasanya meneruskan informasi yang diterima dari Beek ke dinas intelijen Australia. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sulit dicari jawabnya. Kecuali kalau kita diijinkan membuka arsip-arsip, terutama arsip Santamaria.
Dari sisi organisasi, ketika kudeta G30S gagal, kader-kader Beek segera mengisi posisi-posisi penting dalam gerakan oposisi terhadap Soekarno. Kelompok ini yang paling siap dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain. Sehingga tidak heran jika kader-kader Beek termasuk yang pertama dari kalangan sipil yang bergabung dengan Soeharto dan militer.
Selain film “Pengkhianatan G30S/PKI” dan buku putih[38] tentang kudeta yang gagal itu, hampir tidak ada kajian sejarah independen yang membahas saat-saat gagalnya percobaan kudeta G30S dan usaha-usaha lanjutannya dalam perebutan kekuasaan. Film “Pengkhianatan G30S/PKI” dibuat untuk kepentingan propaganda rezim Orde Baru. Sementara itu, buku putih versi Orde Baru tersebut kabarnya dibuat di Santa Monica, California, Amerika Serikat. Adalah Guy Pauker, staf think tank RAND Corporation, yang mengundang Ismail Saleh, SH dan Brigjen TNI Nugroho Notosusanto ke Santa Monica untuk menulis buku putih tersebut sebagai tandingan atas Cornell Paper.[39]
Kajian seperti ini sangat penting karena di masa-masa dini inilah sesungguhnya seluruh narasi Orde Baru dibentuk. Misalnya, siapa yang menasehati Soeharto untuk membentuk opini bahwa PKI-lah yang berada di balik kudeta gagal G30S? Siapakah yang memberikan nasehat untuk menciptakan mitos keji bahwa Gerwani yang menari dan menyilet tubuh para jendral yang dibunuh? Untuk tujuan apa? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu penting diajukan dan dicari jawabannya.
Antara Kader dan ‘Apparatchik’ Rezim Orde Baru
Kader-kader Pater Beek memegang peranan menentukan dalam proses kudeta merayap oleh Soeharto untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno. Tanggal 2 Oktober, hanya sehari setelah usaha kudeta ini digagalkan, Harry Tjan bersama aktivis-aktivis HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) sudah membentuk Komite Aksi Pengganyangan Gestapu (KAP-Gestapu). Organisasi ini mendapat dukungan penuh dari Soeharto dan militer yang berpihak kepadanya. Pada akhir bulan Oktober 1965, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) terbentuk. Ketuanya adalah Cosmas Batubara, yang adalah juga Ketua Presidium PMKRI dan kader Beek.
Di tingkat nasional, kader-kader Beek adalah sekumpulan anak-anak muda kelas menengah atas – sebagian adalah keturunan Tionghoa – yang terbiasa bergaul dengan kalangan elit politik baik sipil maupun militer. Latar belakang ini membuat mereka agak terisolasi dengan keadaan di daerah-daerah, khususnya yang berkaitan dengan pembantaian massal tahun 1965.
Seorang narasumber mengklaim bahwa kondisi para kader Beek ketika itu sama dengan kebanyakan orang di Jakarta. Mereka sama sekali tidak mengikuti (tepatnya: tidak peduli) dengan apa yang terjadi di daerah-daerah. Mereka tahu banyak anggota PKI yang ditahan namun tidak sadar bahwa telah terjadi pembantaian besar-besaran, khususnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Namun kemungkinan bahwa kader-kader di daerah-daerah juga berpartisipasi dalam pembantaian ini tidak bisa diabaikan. Hampir semua organisasi non-PKI pada saat itu ikut dalam pembantaian.
Namun tidak dapat diabaikan juga bahwa kader-kader Beek di tingkat nasional ikut berpartisipasi dalam menciptakan narasi yang menghubungkan usaha kudeta G30S dengan Partai Komunis Indonesia dan mendukung narasi-narasi kekejaman PKI yang kemudian tidak terbukti kebenarannya itu. Tidak dapat disangkal bahwa narasi seperti anggota Gerwani yang menyilet wajah para jenderal yang diculik dan memotong kemaluannya telah menimbulkan provokasi terhadap massa di tingkat bawah. Narasi-narasi seperti ini telah mendorong terjadinya pembantaian besar-besaran terhadap anggota-anggota PKI. Hingga saat ini, belum ada penyelidikan yang mendalam tentang siapa yang menciptakan narasi-narasi ini ketika muncul pertama kali.[40]
Dengan tiba-tiba golongan Katolik, sebuah minoritas yang amat kecil dalam masyarakat Indonesia, memiliki pengaruh yang amat besar. Pengaruh itu disalurkan lewat pembantu-pembantu terdekat Soeharto, khususnya Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani. Mereka adalah orang-orang kepercayaan Soeharto dan sudah mendampingi dia sejak masih menjabat Panglima Kodam Diponegoro di Jawa Tengah.
Kita tidak tahu sejak kapan kader-kader Beek mengenal salah satu dari kedua orang ini atau berhubungan dengan Soeharto secara langsung.[41] Yang jelas kader-kader Beek, khususnya Harry Tjan, Jusuf Wanandi dan saudaranya Sofjan Wanandi memiliki akses yang sangat besar terhadap Soeharto lewat Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani.
Ali Moertopo adalah orang intelijen. Dia dikenal memiliki jaringan intelijennya sendiri yang disebut Opsus (Operasi Khusus). Jaringan intelijen ini berada di luar struktur dinas intelijen negara. Opsus memiliki akses langsung ke Soeharto dan dioperasikan seperti intelijen pribadinya.
Setelah ‘kemenangan’ terhadap PKI, tentu kader-kader yang jumlahnya ribuan ini harus melanjutkan hidup secara normal. Mereka membutuhkan pekerjaan. Banyak dari mereka yang masuk ke pemerintahan atau ke lembaga-lembaga yang baru dibentuk. Kader-kader Beek banyak mengisi posisi di dalam Golkar, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kader-kader ini juga banyak mengisi Bapilu (Badan Pemenangan Pemilu) Golkar yang sangat berperan dalam ‘membuldozer’ partai-partai politik pada Pemilu tahun 1971 dan memenangkan Golkar.[42]
Tidak dapat dipungkiri, kader-kader Beek sukses menciptakan cetak biru (blue-print) sistem politik Orde Baru. Mereka berada di balik penciptaan Golkar, penyederhanaan sistem kepartaian, dan memenangkan Golkar dengan segala cara pada Pemilu tahun 1971. Dalam hal ini, mereka bekerjasama dengan erat dengan militer. Semua ini memberikan landasan yang kokoh untuk Orde Baru.
Ironisnya, kader-kader Beek jugalah yang mematikan Partai Katolik, yang dibubarkan pada bulan Desember 1972. Padahal Harry Tjan, salah seorang sekondan terdekat Beek, adalah Sekjen partai ini. Argumen yang dipakai adalah golongan Katolik harus masuk ke kekuatan politik dimana mereka bisa berperan (baca: berkuasa). Beek dan kader-kadernya seringkali mengutip perumpamaan sebagai ‘garam.’ Orang Katolik harus menjadi garam yang jumlahnya kecil namun menjadi penentu rasa dalam makanan. Inilah alasan utama untuk membubarkan Partai Katolik. Dengan dibubarkannya Partai Katolik, kader-kader Beek bebas masuk ke Golkar tanpa dicurigai sebagai penyusup dari Partai Katolik. Sementara, para politisi bekas Partai Katolik yang tidak masuk ke Golkar dialihkan ke Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang dipaksakan pembentukannya pada tahun 1973.
Sebagian dari kader-kader ini masuk ke dalam Opsus, jaringan intelijen yang dikendalikan Ali Moertopo. Kader-kader Beek berperan sangat besar dalam memenangkan Penentuan Pendapat Rakyat (The Act of Free Choice) atau Pepera tahun 1969. Ini adalah pemungutan suara untuk menentukan apakah Papua Barat akan bergabung dengan Indonesia ataukah menjadi negara tersendiri. Indonesia sukses meyakinkan PBB supaya Pepera tidak dilakukan dengan suara terbanyak rakyat Papua, tetapi ditentukan secara ‘mufakat’ lewat perwakilan. Ada 1,026 orang yang dikategorikan berhak untuk memilih pada Pepera tersebut. Lewat operasi intelijen, mereka semua bermufakat untuk bergabung dengan Indonesia. Di kemudian hari banyak dari orang-orang ini mengatakan bahwa Pepera sebenarnya adalah “the act of no choice” karena begitu hebatnya intimidasi dan manipulasi terhadap mereka yang berhak memilih.
Kader-kader Beek masuk ke Papua sebagai relawan dan merekalah yang menjadi ujung tombak operasi intelijen. Ironisnya, di Papua mereka berhadapan dengan gereja Katolik dan gereja-gereja Kristen lain yang sudah lebih dahulu hadir menjalankan misi di sana. Bentrokan antara kader-kader awam yang Katolik dengan gereja Katolik lokal tidak dapat dihindari. Pada saat itu, semua uskup Katolik di Papua Barat menyatakan mendukung Pepera asal dilakukan lewat mekanisme ‘satu orang, satu suara’ (one man, one vote). [43]
Kelihatan sekali kontras antara kader-kader Katolik ini dengan hirarki gereja Katolik lokal yang mencoba melindungi umatnya. Kader-kader Beek juga menekan gereja Katolik Indonesia untuk mendukung penyatuan Papua tersebut. Ketua MAWI (Majelis Agung Waligereja Indonesia)[44] saat itu, Mgr. Justinus Kardinal Darmojuwono, Pr. menulis surat kepada hirarki gereja di Papua[45] yang menjelaskan bagaimana sebaiknya posisi gereja Katolik dalam hal Pepera. Surat itu dikonsep oleh intelijen Indonesia dan diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda oleh Drs. Lo Shiang Hien Ginting.[46] Setelah beberapa lama, Mgr. Darmoyuwono mengaku hanya diminta menandatangani surat tersebut
Tekanan kepada gereja Katolik lokal Papua pun tidak dapat dihindarkan. Bahkan seorang Yesuit Indonesia yang bekerja untuk Keuskupan Jayapura merasa keberatan. Pater Henricus Hadipranata, SJ saat itu berkomentar, “Buat apa dapat Irian Barat kalau di dunia internasional nama Indonesia menjadi jelek?”
Frank Mount memuji setinggi langit peranan kader-kader Beek dalam Pepera ini. “Sekitar seratusan orang yang dilatih khusus oleh Beek dikirim ke Irian Jaya untuk mendorong agar rakyat memilih penyatuan dengan Indonesia. Mereka semua memberi laporan kepada Beek yang kemudian meneruskannya kepada Ali Moertopo tentang apa yang dibikin oleh orang-orang militer karena Moertopo tidak pernah percaya pada apa yang dikatakan oeh para perwira-perwiranya yang berada di lapangan jauh dari Jakarta.”[47]
Tidak berhenti hingga Pepera. Kader-kader Beek juga ikut mengambil peranan dalam operasi intelijen untuk menginvasi Timor Leste tahun 1975. Banyak dari mereka yang terlibat dalam “operasi Komodo,” yang masuk ke Timor Leste sebagai relawan bersama dengan militer yang menanggalkan semua atribut kemiliterannya.
Namun peran kader-kader Beek paling besar terjadi pada tingkat diplomasi internasional. Pada saat itu, Harry Tjan dan Jusuf Wanandi diserahi tugas untuk berkomunikasi dengan Australia. Komunikasi dua konfidan terdekat Beek dengan Australia ini terekam pada sebuah buku setebal 900 halaman yang terbit pada tahun 2000, setahun setelah Timor Leste melakukan jajak pendapat dan akhirnya memilih merdeka dari Indonesia. Dalam buku yang memuat semua kabel dari Jakarta ke Canberra serta lalu lintas komunikasi dengan pihak Indonesia itu, terlihat bagaimana pentingnya peranan Harry Tjan dan Jusuf Wanandi.[48]
Yang lebih menarik lagi, ternyata Harry Tjan tidak hanya memainkan saluran-saluran diplomatik saja. Dia juga berhubungan dengan kawan-kawannya di kelompok BA Santamaria dan berusaha memainkan opini publik Australia lewat pengaruh kawan-kawannya ini. Frank Mount memperlihatkan bagaimana sikap Indonesia sebelum invasi. Dalam suratnya ke Santamaria pada 21 Juli 1974, misalnya, Mount berkesimpulan bahwa sikap Indonesia sudah jelas, yakni hendak memasukkan Timor Leste ke dalam wilayah Indonesia. Dalam surat itu juga digambarkan bagaimana Harry Tjan mengatur strategi untuk membentuk opini di kalangan pengambil kebijakan di Australia.[49]
Pada akhirnya, kader-kader yang semula dilatih untuk menjadi ‘intelektual’ dan aktivis ini dalam perjalanan waktu akhirnya hanya menjadi ‘apparatchik’ atau aparat Orde Baru. Banyak dari kader yang berkarir di Golkar akhirnya didepak ketika Soeharto mengubah partner yang menjadi aliansi kekuasaannya.
Gereja Katolik, Yesuit, dan Politik
“… [P]ada waktu gereja-gereja dibakar, dimana militer? Kalau kita mau mantap di Indonesia, maka bukan karena dilindungi oleh militer, melainkan karena berhubungan baik dengan saudara-saudara Muslim sendiri.”
Franz Magnis-Suseno.[50]
Tidak pelak lagi, Beek dan kader-kadernya menimbulkan ketegangan tersendiri di dalam gereja Katolik dan di dalam Serikat Yesus. Di kalangan gereja, keluhan-keluhan mulai muncul karena kader-kader Beek, yang merasa lebih superior dari umat biasa dan bahkan dari pastor-pastor paroki, mulai menciptakan keresahan di kalangan komunitas umat. “Setelah tidak ada yang dimakan di luar, mereka mulai makan ke dalam,” demikian seorang pastor tua mengatakan pada saya.
Gereja takut mengambil tindakan karena kelompok ini memiliki akses yang sangat besar ke dalam kekuasaan. Namun konfrontasi antara pihak gereja dengan kelompok Pater Beek terjadi juga. Suatu kali Provinsial Yesuit Indonesia, Paulus Suradibrata, SJ bersama Uskup Agung Jakarta Mgr. Leo Soekoto, SJ harus berhadap-hadapan dengan Beek yang ditemani Harry Tjan dan Jusuf Wanandi. Kedua petinggi gereja itu mempertanyakan tujuan, materi, dan metode pembinaan. Pertemuan berlangsung panas. Harry Tjan menuduh Mgr. Leo Soekoto sebagai ‘Ponsius Pilatus,’ yang hendak cuci tangan saat mengadili Yesus.[51]
Hubungan dengan sesama Yesuit juga tidak kalah kontroversial. Persoalan Beek, seperti yang sudah kita lihat, ternyata menarik perhatian langsung dari Roma. Soedjati Djiwandono menulis bahwa Jenderal Jesuit sendiri, Pedro Aruppe, SJ, yang memerintahkan Beek menutup kaderisasinya.
Namun benturan antara sesama Yesuit ini seringkali tidak dapat dihindarkan. Konggregasi ini mendorong anggota-anggotanya bekerja dan membangun karya sendiri. Kadang terjadi gesekan yang cukup hebat antara sesama Yesuit, terlebih antara Yesuit yang memiliki karya serupa. Yang lebih parah adalah benturan yang bersifat ideologis. Ini pernah terjadi di Filipina pada tahun 2007. Penasehat keamanan nasional (NSA atau National Security Adviser) pada Presiden Gloria Macapagal Arroyo di Filipina, adalah seseorang yang bernama Norberto Gonzales. Dia adalah kawan BA Santamaria dan hadir secara reguler pada acara-acara konferensi Pacific Institute. Pada tahun tersebut, lebih dari 800 aktivis kiri dibunuh oleh pemerintahan Arroyo. Ideologi yang teramat kanan dari Gonzales ini mendapat dukungan dari seorang Yesuit, Pater Romeo “Archie” Intengan, SJ. Pater Intengan adalah aktor intelektual di balik Partidong Demokratiko Sosyalista ng Pilipinas atau Democratic Socialist Party[52] of the Philippines, partai dimana Gonzales dan Arroyo bergabung. Intengan adalah guru politik dari Gonzales.
Sementara, para aktivis kiri yang dibunuh Gonzales kebanyakan berasal dari CPP-NDF (Communist Party of the Philippines-National Democratic Front). Partai ini dipimpin oleh Jose Maria Sisson. Yang lebih menarik adalah guru politik dan spiritual Sisson adalah juga seorang Yesuit, Jose Blanco, SJ. Kedua faksi ini bertarung hingga berdarah-darah di medan politik namun mereka tetap berada dalam satu konggregasi.
Di Indonesia memang tidak separah itu, namun bukan berarti tidak ada. Salah satu pengkritik paling keras Pater Beek di dalam Yesuit adalah seorang pastur Jawa, Pater F. Danuwinata, SJ. Kritik dari Danuwinata berkisar pada pemihakan pada masyarakat atau mengabdi pada kepentingan elit. Untuk Danuwinata apa yang dikerjakan oleh Beek sepenuhnya untuk mengabdi pada elit. Hal yang serupa juga dikatakan oleh Pater Franz Magnis-Suseno, seorang Yesuit Jerman yang lama bekerja di Indonesia.
Kritik yang lain datang dari para politisi dan aktivis politik Katolik. Pertanyaan yang diajukan adalah apakah tindakan membubarkan Partai Katolik itu tepat? Haruskah menjadi ‘garam’ itu (meminjam semantik yang selalu dipakai oleh kader-kader Beek) selalu identik dengan kekuasaan dan nafsu berkuasa? Bukankah lebih baik memiliki Partai Katolik, dengan identitas dan prinsip yang jelas, sehingga orang-orang Katolik bisa dengan jujur berdialog dan bekerjasama dengan kelompok masyarakat lain? Bukankah dengan membuka identitas itu secara moral lebih bisa dipertanggungjawabkan ketimbang menyusup dan melakukan infiltrasi?
Pada akhirnya, fenomena Beek dan kelompoknya yang kita hadapi di sini tidak jauh berbeda dengan ulama atau agamawan dari kelompok agama lain yang memakai agama untuk mencapai kepentingan politiknya. Gereja Katolik Indonesia turut menanggung beban moral itu. Mungkin sudah waktunya gereja berpikir untuk meminta maaf secara tulus kepada korban-korban pembantaian 1965, rakyat Papua (yang punya cukup banyak pemeluk Kristen) dan rakyat Timor Leste (yang hampir 90 persen Katolik). Ironi terbesar menjadi orang Katolik Indonesia adalah menanggung beban korban yang sebagian besar adalah umat Kristen/Katolik sendiri. ***
—————
[1] Frank Mount, Wrestling with Asia, Connor Court Publishing: Ballan, Victoria, Australia, 2012.
[2] Ibid., hal. 3
[3] Ibid., hal. 125-126.
[4] Lihat Patrick Morgan (ed.), Your Most Obedient Servant: B.A. Santamaria: Selected Letters, 1938-1996, Melbourne: Melbourne University Press, 2007, p. 269.
[5] Mgr. Nguyen Van Thuan ditahbiskan menjadi Uskup Agung Saigon pada 24 April 1975 setelah sebelumnya menjadi uskup di Nha Trang. Enam hari, setelah menjadi Uskup Agung, Saigon jatuh ke tangan tentara Vietnam Utara. Mgr. Nguyen kemudian ditahan di kamp reedukasi selama 13 tahun, termasuk selama sembilan tahun dalam ruang tahanan isolasi. Dia meninggal di pengasingan pada tahun 2002. Pada tahun 2007, Vatikan memulai proses beatifikasi atas Mgr. Nguyen Van Thuan, sebuah proses yang akan mengangkatnya menjadi seorang santo.
[6] Lihat, Kevin Peoples, “Reflections on the adventures of Frank Mount,” Social Policy Connections, 19 Oktober 2012. http://www.socialpolicyconnections.com.au/?p=5572
[7] Frank Mount, op.cit. hal. 331.
[8] Ibid. Hal. 113.
[9] Dalam hal ini, Frank Mount, ibid. hal. 113-4, mengutip dokumen yang diedit oleh Partick Morgan, op.cit. hal. 545.
[10] Frank Mount, ibid. hal. 121.
[11] Dalam pandangan Katolik manusia terdiri atas roh dan daging (badaniah). Manusia harus hidup dari roh dan menjauhi kesenangan daging (badaniah).
[12] Frank Mount, op. cit. hal. 121.
[13] Ibid. hal. 257-8.
[14] Cukup mengesankan bahwa para pastur Belanda ini sudah memakai atribut Pancasila pada tahun 1950an, persis ketika pertentangan ideologis antara partai-partai politik mencapai puncaknya. Mereka bahkan belum menjadi warganegara Indonesia ketika itu. Kita tahu bahwa pemakaian atribut Pancasila menjadi sangat meluas di zaman Orde Baru. Banyak dari kader-kader dari jaringan kaderisasi Pater Beek yang menjadi ‘ideolog’ rezim ini.
[15] Pekerjaan seorang pamong atau perfect adalah mendisiplinkan para siswa.
[16] J.B. Soedarmanta, Pater Beek, SJ: Larut Tetapi Tidak Hanyut, Jakarta: Penerbit Obor, 2008. Hal 103.
[17] Setelah mengalami beberapa perubahan Sodality of the Blessed Virgin Mary kemudian berubah menjadi Christian Life Community (CLC) atau di Indonesia menjadi Komunitas Hidup Kristiani (KHK). Kelompok ini sangat jauh berbeda dengan sewaktu dikelola oleh Beek yang sangat militan dan berorientasi sangat politis.
[18] Ini diakui oleh Harry Tjan dalam wawancara dengan Forum Alumni Asrama Realino, 5 Agustus 2003. https://forsino.wordpress.com/2008/07/05/romo-beek/
[19] Konggregasi Maria untuk para sarjana diketuai oleh Prof. Dr. Jusuf Pang Lay Kim (sering ditulis Panglaykim) atau J.E. Pangestu. Dia adalah seorang ekonom yang kemudian bergabung ke CSIS. Putri Dr. Panglaykim adalah Dr. Mari Elka Pangestu, yang menjadi menteri di kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
[20] Paroki adalah unit paling bawah dalam hirarki gereja Katolik. Setiap paroki dipimpin oleh seorang imam (pastur) dan biasanya dilengkapi dengan paling tidak satu gereja.
[21] Y.B. Soedarmanta, op.cit. hal. 131.
[22] Ibid. hal. 137
[23] Artinya, orang yang memiliki semangat kerasulan, yaitu semangat untuk menyebarkan ajaran Kristen lewat tingkah laku dan tindakan sehari-hari.
[24] J.B. Soedarmanta, op. cit., hal. 143-4.
[25] http://www.hidupkatolik.com/2013/05/21/kader-katolik-menurut-romo-beek
[26] JB Soedarmanta, op.cit. hal. 184-200.
[27] Tidak jelas acuan majalah apa yang dimaksud oleh Soedjati Djiwandono ini.
[28] Soedrajat Djiwandono adalah adik dari Soedjati Djiwandono. Dia kemudian menjadi Gubernur Bank Indonesia di bawah Orde baru (1993-1998).
[29] Perlu diingat bahwa fundamentalisme agama tidak ada hubungannya dengan kesalehan dalam beragama. Fundamentalisme agama adalah sebuah sikap politik yang menjadikan agama sebagai landasan kepentingan dalam mengambil tindakan politik.
[30] Liga Demokrasi dibentuk 24 Maret 1960 untuk mengimbangi kekuasaan Soekarno. Kelompok ini didirikan oleh pemimpin-pemimpin Masyumi, PSI, NU, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Katolik, PSII, dan Parkindo.
[31] Yusuf Wanandi, Shades of Grey: A Political Memoir of Modern Indonesia 1965-1998, Singapore and Jakarta: Equinox Publishing, 2012.
[32] Ibid. hal. 20.
[33] Frank Mount bercerita dalam memoarnya bahwa Beek pernah ditahan oleh polisi dan Biro Dokumentasinya digeledah. Kejadian itu membuat Ali Moertopo berkeinginan untuk melindungi Beek dan semua dokumentasinya. Moertopo memberinya ruang di sebuah kantor riset swasta lengkap dengan apartemen untuk tinggal. Namun Beek menolak dengan tegas tawaran itu. op.cit. hal. 121-2.
[34] Wanandi, op.cit. hal. 32. Pernyataan ini sulit untuk dibuktikan. Kenyataannya, PKI adalah sebuah partai besar dengan 20 juta anggota. Sementara jumlah orang Katolik di seluruh Indonesia saat itu hanya berkisar dua juta orang saja. PKI tidak pernah menganggap orang Katolik sebagai ancaman yang serius karena hanya minoritas kecil.
[35] Tentu bukan hal yang mudah untuk mencetak dua hingga tiga ribu kader. Apalagi melengkapinya dengan segala macam peralatan seperti yang disebutkan oleh Wanandi di atas. Kalau klaim ini benar, tentu dibutuhkan logistik dan dana yang luar biasa besar. Darimana sumber dana ini? Sumber-sumber di kalangan Yesuit mengatakan hampir bisa dipastikan bahwa Serikat tidak akan membiayai kegiatan dengan dana sebesar itu. Demkian pula dengan gereja Katolik. Seorang sumber mengatakan bahwa gereja Katolik Indonesia terkategori gereja miskin. Ada banyak kebutuhan yang jauh lebih mendesak untuk dipenuhi ketimbang menciptakan kader politik.
[36] CGMI adalah singkatan dari Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia, organisasi mahasiswa yang berafiliasi pada PKI.
[37] Jusuf Wanandi, op.cit. hal. 34.
[38] Lihat, Gerakan 30 September, pemberontakan Partai Komunis Indonesia: latar belakang, aksi, dan penumpasannya, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1994.
[39] Wanandi, op.cit. hal. 181. Cornell Paper adalah sebuah analisis sementara yang dikerjakan oleh Benedict Anderson, Ruth McVey, dan dibantu oleh Fred Bunnell, A preliminary analysis of the October 1, 1965, coup in Indonesia, Ithaca, NY: Cornell Modern Indonesia Project, 1971.
[40] Seorang sejarawan yang saya temui dalam satu seminar di Universitas Yale mempertanyakan hal ini. Siapa yang mengonstruksi narasi tentang Gerwani? Adakah keterlibatan kader-kader Beek dalam penciptaan narasi oleh koran-koran militer yang terbit saat itu? Kita tahu, setelah kudeta G30S gagal, militer melarang semua publikasi dan penyebaran informasi. Yang boleh terbit hanya koran Berita Yudha dan Angkatan Bersenjata. Lewat kedua koran inilah narasi tersebut disebarkan.
[41] Jusuf Wanandi menulis bahwa dia bertemu dengan Ali Moertopo pertama kali pada tahun 1963 di satu seminar yang diadakan Kostrad. Wanandi, op.cit., hal. 66.
[42] Detail tentang peranan Wanandi dalam memenangkan Golkar, lihat hal. 103-107.
[43] Para uskup di Papua adalah imam yang berkewarganegaraan Belanda. Mereka adalah Mgr. Rudolf Josef Staverman OFM dari Jayapura, Mgr. H. Tilleman, MSC dari Merauke, dan Mgr. Pieter van Diepen OSA dari Manokwari. Lihat juga, JB Soedarmanta, op. cit. hal. 225.
[44] Sekarang menjadi Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).
[45] Pada tahun 1967, Vatikan memasukkan gereja Katolik di Papua sebagai bagian dari wilayah provinsi Indonesia.
[46] Aktivis Golkar yang kemudian berganti nama menjadi Drs. Lohena Ginting.
[47] Frank Mount, op. cit. hal. 258.
[48] Documents on Australian Foreign Policy, Australia and the Indonesian Incorporation of Portuguese Timor, 1974-1976, Department of Foreign Affairs and Trade and Melbourne University Press, 2000. Jusuf Wanandi dalam memoarnya mengatakan bahwa para diplomat yang berhubungan dengannya dan tercatat dalam dokumen-dokumen ini salah menginterpretasikan perannya. Dia mengklaim tidak memiliki pengaruh sebesar yang digambarkan dalam dokumen-dokumen tersebut.
[49] Frank Mount, op. cit. hal. 270-271.
[50] Menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat majemuk, Jakarta: Obor, 2004, hal. 150.
[51] Fragmen ini diambil dari JB Soedarmanta, hal. 234. Seorang imam yang bekerja untuk Keuskupan Agung Jakarta pernah mendengar cerita ini namun tidak bisa mengingat kapan persisnya pertemuan itu terjadi dan apa yang menjadi pokok persoalan. Namun dia mengakui bahwa hubungan antara Beek dan Khasebulnya dengan pihak gereja selalu dalam ketegangan.
[52] Nama ‘Democratic Socialist’ di sini sangat memperlihatkan pengaruh Santamaria. Frank Mount dalam memoarnya membedakan secara tegas antara ‘Democratic Socialist’ yang dianggapnya mirip dengan masyarakat di negara-negara Barat industrial dengan ‘Socialist Democratic’ yang Marxis.
Oleh Made Supriatma
Harian IndoPROGRESS
Ilustrasi oleh Alit Ambara (Nobodycorp)